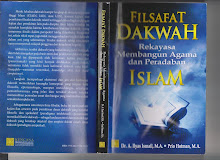Oleh: Prio Hotman
Sejak fenomena lengsernya Ben Ali dari singgasana kepresidenan Tunisia, negara-negara Arab lain di Timur Tengah seolah mendapatkan legitimasinya untuk “latah” memunculkan revolusi. Awalnya diikuti oleh revolusi Tahrir yang berakhir dengan lengsernya kekuasan absolut Presiden Mubarok yang bertahan selama tidak kurang dari tiga dekade. Kini negara-negara seperti Libya, Bahrain, Jordania dan bahkan negara paling konservative di dunia sekelas Arab Saudi pun tidak mau ketinggalan ambil peran dalam trend revolusi Arab ini. Terkait dengan yang tersebut terakhir ini, saya melihat ada suatu keunikan yang tidak ditemukan pada fenomena revolusi di negara-negara Arab yang lain. Jika di negara-negara semisal Tunisia, Mesir, dan Libya para ulama mereka bersikap pro, atau kurang lebih tidak mencela munculnya revolusi, maka sikap demikian ini tidak kita temukan pada pandangan ulama-ulama kerajaan Arab Saudi. Alih-alih membela para demonstran yang menuntut perubahan, para ulama mereka justru memfatwakan bahwa demonstrasi sebagai suatu perbuatan terlarang yang tidak islami. Lebih dari sekedar fatwa, ulama-ulama itu malah menuduh bahwa demonstrasi yang terjadi belakangan di negara itu sebagai sebuah kedurhakaan yang tak terampuni. Walaupun tidak langsung bersinggungan dengan iklim politik demikian itu, kita tentu dapat berempati bahwa fatwa yang naif itu pasti amat melukai dan mematahkan semangat para demostran.
Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sekarang, kubu demonstran di Arab Saudi yang mengecam penindasan dan monarki absolut itu mesti berhadapan dengan dua kekuatan yang berkonspirasi, kekuatan politik dan kekuatan doktrin agama. Dari kekuatan politik, kubu demonstran bersitegang dengan keganasan para tentara kerajaan yang akan “mengeksekusi” setiap orang yang bersuara menuntut perubahan. Seolah tidak cukup dengan kekerasan fisik, para ulama Saudi ikut-ikutan mengintimidasi para pejuang keadilan itu dengan cara melemahkan psikologi mereka dengan doktrin-doktrin agama versi mereka. Salah satu fatwa yang terkesan parodis seperti dilansir oleh Republika, adalah pernyataan mereka bahwa perubahan tidak bisa dilakukan dengan cara menghasut, tapi dengan cara nasehat yang islami. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bilakah para raja dan pangeran yang absolut itu mau mendengarkan nasehat dari rakyat? Tidakkah mereka yang mengaku sebagai pengawal hukum Tuhan itu pernah mendengar sabda Nabi “kebijakan pemimpin itu mengikuti kemaslahatan rakyatnya?” Ataukah ini hanya sebuah lelucon bagi sebuah negara yang bersimbolkan syahadat dan berkonstitusikan Kitab Allah?
Dimaklumi bahwa perkawinan agama dan politik yang terjadi di kerajaan Arab Saudi sejatinya merupakan konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mengukuhkan doktrin dari sebuah sekte yang tidak terhitung dalam sejarah pemikiran Islam ke pentas dunia. Banyak pengamat yang menilai bahwa seandainya tanpa dukungan politik Ibn Saud dan penerusnya, ideologi wahabi mungkin tidak bisa berkembang seperti sekarang. Mungkin karena “hutang budi” itulah, para ulama Saudi yang notabene beraliran wahabi merasa perlu memberi dukungan terhadap praktik politik absolut kerajaan. Mungkin hikmah yang bisa kita petik dari kasus konspirasi ulama dan praktik absolutisme politik ini barangkali mengingatkan kita kembali kepada pentingnya proyek sekularisasi negara yang belakangan ini mulai kelihatan melemah apinya. Semenjak munculnya fenomena kebangkitan agama-agama dewasa ini, ada kesan seolah sekularisme kehilangan kepercayaan dirinya dan takluk dengan rongrongan agama. Ini ditunjukkan terutama oleh kompromi-kompromi politik yang akhirnya menerima tuntutan kelompok agama tertentu dan menjadikannya sebagai public policy yang mengikat bagi semua warga negara. Mungkin menjadikan kasus konspirasi ulama-absolutisme politik di Saudi sebagai analogi untuk menganalisa suasana ketegangan politik dan agama di Indonesia tidak sepenuhnya tepat sasaran. Namun demikian, fenomena yang kita saksikan sekarang di negara kita, terkait dengan beberapa kasus yang menuntut agar pemahaman agama tertentu atau fatwa ulama dijadikan sebagai konstitusi jika dibiarkan bukan tidak mungkin akan mengarah kepada bentuk otoritarianisme seperti yang terjadi di Saudi.
Kerajaan Saudi, adalah contoh buruk bagaimana agama dan para ulamanya ikut campur dalam urusan kenegaraan dan pengaturan publik. Adapun saat ini, mata dunia melihat bahwa loyalitas rakyat pada apa yang didoktrinkan sebagai “konstitusi yang suci” tidak lagi dapat dipertahankan. Demonstrasi yang muncul di Arab Saudi dapat dilukiskan sebagai suara hati nurani manusia yang terdalam yang berteriak bahwa “agama” dan “konstitusi yang suci” semata-mata tidak cukup untuk menjadi dasar pengaturan negara terhadap kebijakan publik. Walaupun masih terkesan takut dan malu-malu, berkumpulnya 12 orang di depan pintu Masjid al Rajhi di ibu kota Riyadl yang menuntut perubahan monarki absolut menjadi kerajaan konstitusional itu, jelas sekali menunjukkan bahwa untuk menciptakan suatu negara yang berkeadilan dan pro rakyat, butuh lebih dari sekedar campur tangan ulama dan undang-undang suci (baca: hukum Islam) dalam menentukan wajah sebuah bangsa. Untuk saat ini, mungkin kita masih sulit untuk memprediksi apakah kelanjutan revolusi di Arab Saudi itu akan berakhir seperti di Tunisia dan Mesir, ataukah kemenangan akan berpihak pada kelompok otoriter dan para ulama konspiratifnya dengan cara “membunuh” suara para demonstran.
Mungkin terlalu simplistis mengatakan bahwa otoritarianisme politik semata lahir dari agama. Dengan tidak melupakan contoh otoritarianisme komunis, tapi sejarah kelam politik Islam tentang mihnah, dan ditambah lagi sekarang contoh kasus Arab Saudi yang mutakhir, menjadi bukti bahwa agama dengan kosnpirasi ulamanya merupakan salah satu varian yang ditengarai berpotensi melahirkan otoritarianisme politik. Melalui pernyataan di atas, saya ingin mengajak para pemerhati dan aktivis pembaruan untuk kembali komitmen kepada proyek sekularisme politik di Indonesia yang selama ini telah diperjuangkan. Mungkin kita tidak akan mencontoh model sekularisme “leicite” yang pernah diterapkan Prancis atau Turki, tapi kita tetap akan memperjuangkan sekularisme politik dalam format yang bukan hanya ramah terhadap agama, tapi juga tegas. Ramah dalam arti memberikan ruang bagi para pemeluk agama untuk mengekspresikan keyakinannya, dan tegas dalam arti tidak berkompromi dengan segala bentuk tekanan-tekanan kelompok tertentu yang hendak memaksakan keyakinannya sebagai pengatur kebijakan publik.
Untuk memperjuangkan model sekularisme politik seperti yang disebut di atas, kiranya poin-poin berikut ini dapat menjadi pertimbangan.
Pertama, memisahkan lembaga-lembaga institusi keagamaan seperti MUI dari domain negara. Dengan memutus aliran anggaran belanja negara ke lembaga-lembaga keagamaan tersebut, menandakan sebuah sikap yang tegas bahwa negara tidak ingin dibebani dengan urusan-urusan yang bersifat privat seperti persoalan agama dan keyakinan. Negara dalam hal ini bisa memberi perlindungan dalam bentuk perizinan eksistensi dengan pembiayaan swadaya internal. Dengan begitu, maka setiap fatwa atau statemen yang dikeluarkan lembaga agama tersebut tidak lagi memiliki daya ikat konstitusional kepada semua warga negara.
Kedua, mencabut dukungan terhadap partai-partai politik dan sistem keuangan yang berbasis agama. gagasan yang mesti diusung oleh sebuah partai politik dalam sistem sekuler adalah merujuk kepada idealisme bersama kebangsaan yang diwujudkan dalam induk konstitusi, dan bukan pada idealisme kelompok tertentu. Begitupun sistem keuangan negara harus diatur secara merata, dan bukan berfokus untuk kesejahteraan golongan tertentu.
Ketiga, mencabut pemberlakuan perda-perda syari’at dan menggantinya dengan undang-undang daerah yang disepakati oleh semua kelompok dan elemen masyarakat terkait. Tujuan dari pencabutan perda-perda syari’at tersebut dilakukan demi menghindari praktik otoritarianisme politik dari lini pemerintahan yang terkecil. Melalui konsensus semua kelompok masyarakat, maka pelbagai bentuk aspirasi rakyat dapat diakomodir dan penindasan atas nama dominasi mayoritas dapat dihindari.
Keempat, dalam wilayah edukasi, ketegasan negara terhadap agama bisa diwujudkan dalam bentuk revisi kurikulum pendidikan. Dalam hal ini, mata pelajaran agama di sekolah-sekolah negara mesti dicabut dan digantikan dengan studi etika atau moral yang ramah dengan keragaman. Hal ini dilakukan demi menghindari pemaksaan paradigma kelompok keagamaan tertentu sebagai bidang studi wajib. Mungkin pendekatan multikulturalisme dan kajian lintas keyakinan sudah saatnya dijadikan metode alternatif pembelajaran di sekolah-sekolah sebagai wahana memperkenalkan “yang lain” dan menghapus segala bentuk kebijakan publik yang berbau otoritarian.
http://islamlib.com/id/artikel/otoritarianisme-politik-arab-saudi
Senin, 06 Juni 2011
Reportase Diskusi Bulanan Sila Pertama dan Sila Terakhir Pancasila Bermasalah
Oleh : Prio Hotman
Setelah kurang lebih off dua bulan, diskusi rutin bulanan Jaringan Islam Liberal (JIL) kembali hadir, kamis (25 Mei 2011). Diskusi bulanan kali pertama JIL semenjak mendapat ancaman bom beberapa waktu lalu ini mengambil tema “Indonesia dan Doktrin Pancasila”, dengan menghadirkan dua orang pembicara: Luthfi Assyaukanie (JIL) dan Yudi Latif (Reform Institute). Secara khusus, tema diskusi kali ini terkait dengan buku terbaru Yudi Latif berjudul Negara Paripurna.
Luthfi Assyaukanie mengawali diskusi dengan bercerita tentang kegiatan peluncuran buku Negara Paripurna beberapa waktu lalu yang sempat ia hadiri. Ia takjub dengan meriahnya ucapan selamat yang diberikan orang atas peluncuran buku ini. “Ucapan selamat untuk buku Yudi Latif ini melebihi ucapan selamat untuk sebuah pernikahan,” katanya.
Apresiasi besar terhadap buku ini, bagi Luthfi, tidak lepas dari konteks mutakhir keindonesiaan yang mem-flashback memori kita ke masa lalu, di mana ancaman terhadap pancasila dan kebebasan beragama kembali terjadi. Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif ini tepat sekali hadir dalam kondisi demikian, dan karenanya wajar jika banyak apresiasi ditujukan kepadanya. Luthfi mengutip ucapan politikus kenamaan PDIP, Taufik Kiemas, yang juga sempat hadir dalam peluncuran buku saat itu: “Inilah buku yang bisa menjadi rujukan kita di tengah kondisi di mana ancaman terhadap pancasila dan kebebasan beragama terulang lagi,” katanya.
Banyaknya pujian atas buku Negara Paripurna, mendorong Luthfi untuk ikut memberikan komentar dan juga kritik atas buku tersebut. Dari judulnya saja, kata Luthfi, penulis buku ini seolah ingin memposisikan diri sebagai Plato dengan negara idam-idamannya, Repubik; atau Al-Farabi dengan al-Madinah al-Fadlilah-nya. Bagi Luthfi, semua konsep negara ideal, seperti dicita-citakan baik oleh Plato, Al- Farabi, dan sekarang oleh Yudi Latif dengan Negara Paripurna-nya itu, merupakan konsep yang utopis, dalam artian tidak realistis, mengawang-awang dan karenanya menjadi sulit untuk diterapkan.
Luthfi juga mengkritik buku ini yang menurutnya terlalu kental nuansa filsafat politiknya. Ia menyarankan, seandainya ditambahkan sedikit saja sentuhan political sciencies, buku ini akan lebih istimewa. Bukan hanya berbicara tentang teori demokrasi misalnya, tapi bagaimana caranya demokrasi itu bisa diterapkan di Indonesia. Namun demikian, Luthfi mengakui ada yang baru dari buku Negara Paripurna Yudi Latif ini. Luthfi terkesan dengan metode penyajian buku ini yang menurutnya mirip dengan tafsir-tafsir klasik, seperti tafsir Al-Thabari misalnya, yang membahas poin-poin secara berurutan. Seperti halnya tafsir-tafsir itu, buku Yudi Latif juga menyajikan bahasan sila-sila dalam pancasila secara berurutan ditambah dengan prolog dan penutup. Pada setiap bahasan sila, dijelaskan alasan posisi urutan sila tersebut, latar belakang kenapa suatu sila itu muncul dan juga wording-nya. Bandingkan dengan tafsir-tafsir klasik yang membahas ayat-ayat secara berurutan dengan menjelaskan munasabah, asbabunnuzul dan mufradat-nya.
Ada banyak buku di dunia ini yang membicarakan masalah Pancasila dalam pelbagai bahasa, dari mulai Indonesia, Inggris dan sebagainya. Jika kita merujuk kepada perpustakaan kongres di Amerika Serikat saja misalnya, kita akan menemukan buku-buku bertema pancasila tidak kurang dari 600-an judul buku, dan buku karya Yudi Latif ini salah satu dari sekian banyak buku tersebut. Banyaknya buku bertema Pancasila menurut Luthfi, merupakan salah satu indikasi bahwa bahasan tentang tema tersebut begitu penting. Hal demikian dapat dipahami, mengingat Pancasila sebagai sebuah ideologi tunggal negara, dihadapkan oleh banyak ideologi lain yang menjadi saingannya. Di sini, kita dihadapkan oleh persaingan ideologi.
Jika merujuk kepada sejarah konsolidasi Pancasila misalnya, menurut teori Deliar Noer yang mengkategorikan kelompok-kelompok perumus Pancasila menjadi muslim- nasionalis dan nasionalis-sekuler, persaingan ketat antar ideologi ketika itu begitu sengit terjadi. Perdebatan ideologi yang paling sengit ketika itu terjadi antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler. Konflik dengan ideologi sosialisme-komunisme juga ada, tapi tidak begitu berarti. Pancasila lahir justru dari persaingan antara dua kelompok tersebut, yang belakangan melahirkan kompromi dalam bentuknya yang sekarang kita kenal. Uniknya, pancasila sebagai kompromi tidak memberikan kepuasan antara kedua kelompok, baik kelompok islamis maupun nasionalis sekuler. Sebaliknya, kedua kelompok itu justru merasa dikecewakan. Ini menjelaskan mengapa hingga kini rongrongan-rongrongan terhadap pancasila terus berdatangan terutama dari kelompok islamis. Terkait ini Luthfi menegaskan, kalaupun ada yang harus kecewa dan dirugikan, justru kelompok nasionalis sekuler-lah yang semestinya merasakan itu, mengingat terlalu besar pengorbanan mereka untuk sampai pada kompromi tersebut.
Dari kritik atas buku Yudi Latif, Luthfi berangkat lebih jauh kepada kritik pancasila sebagai ideologi negara. Luthfi merasa bahwa ada yang salah dengan konstitusi negara kita, khususnya dalam rumusan Pancasila. Sebelum melontarkan kritik, Luthfi dengan santun juga mengingatkan, mungkin kritiknya ini akan dibilang simplifikasi atau mungkin juga “kurang ajar”. Namun begitu, ia berpendapat bahwa sebagai kritik akademis, hal itu wajar belaka. Luthfi memandang dari lima rumusan pancasila, ada dua sila yang bermasalah, yaitu sila pertama (tentang ketuhanan) dan terakhir (tentang keadilan). Tiga sila lebihnya, baginya relatif tidak bermasalah, karena “konsep-negara-modern” bisa menerima itu. Berbeda dengan tiga sila itu, sila pertama yang merupakan representasi landasan ideologi politik, dan sila kelima yang merepresentasikan landasan ideologi ekonomi, bagi Luthfi cenderung rancu dan kacau.
Menjelaskan argumennya atas kritik sila pertama, Luthfi mengatakan, landasan filosofis sangat penting untuk etika bernegara dan bermasyarakat, dan karenanya rumusan yang rasional menjadi sangat penting untuk sebuah konstitusi. Luthfi memberikan contoh betapa buruknya retorika kelompok Islam dalam sejarah ketika mendebatkan sila pertama ini. Kelompok Islam yang ketika itu kalah berargumentasi secara filosofis dengan kelompok nasionalis-sekuler, menunjukkan perilaku yang cenderung tidak objektif (kasus Kasman Singodimejo yang memukul meja karena emosional). Suasana ketika itu bisa dilukiskan betapa kuatnya tekanan kelompok Islam atas sila pertama ini. Ini dibuktikan setidaknya oleh dua hal. Pertama, pemindahan urutan sila dari terakhir menjadi pertama. Kedua, perubahan redaksi rumusan sila ketuhanan, dari ketuhanan yang berkebudayaan seperti dirumuskan Soekarno, menjadi ketuhanan yang maha esa seperti kita kenal sekarang.
Luthfi menyangsikan apakah rumusan sila ketuhanan tersebut akan mampu melewati sejarah, mengingat dalam perjalanannya rumusan demikian itu menyisakan banyak sekali persoalan. Keraguan Luthfi bukannya tanpa alasan. Ia melihat sila pertama ini sangat bias monoteisme. Dengan ideologi yang bias monoteis tersebut, Luthfi menyangsikan apakah Budha dan Hindu misalnya, bisa diterima “secara ikhlas” di negeri ini. Belum lagi fenomena ateisme dan agnostisisme yang belakangan fenomenanya muncul kepermukaan (terkait niat asosiasi kelompok ateisme indonesia yang berniat menyusun buku bertajuk: Apakah Ateisme Dapat Hidup di Indonesia?). Dengan konstitusi yang bias monoteis itu, Luthfi menyangsikan apakah ateisme itu punya prospek legal di Indonesia. Dengan tafsir yang berbeda, seperti pemahaman Buya Syafi’i Ma’arif misalnya, sila pertama memang bisa membuka ruang untuk ateisme. Pertanyaannya: apakah penafsiran seperti itu bisa diterima dikhalayak luas? Jika itu tetap dipertahankan, maka kemungkinannya kita harus bertarung memperebutkan makna dan itu berarti akan sangat melelahkan.
Luthfi juga mengingatkan bahayanya asosiasi agama yang berlebihan terhadap negara, karena bisa melahirkan beberapa masalah. Pertama, konsekuensi penyatuan ideologi agama dan negara dalam kehidupan sosial-politik-keagamaan kita. Lihat misalnya kasus-kasus institusionalisasi agama oleh negara, seperti MUI, Departemen Agama, dan sebagainya. Dengan asosiasi berlebih kepada agama ini, negara juga menjadi terbebani secara moral untuk melindungi institusi-institusi agama tersebut.
Ketika agama dikooptasi oleh negara, maka implikasinya adalah lahirnya diskriminasi mayoritas terhadap minoritas. Luthfi mencontohkan bagiamana sulitnya ia berdebat di Mahkamah Konstitusi ketika membela kelompok minoritas Ahmadiah misalnya. Dalam hal ini, baik Luthfi dan pihak MK sama-sama setuju bahwa negara berkewajiban melindungi agama. Bedanya pembelaan Luthfi mengarah kepada perlindungan agama kepada kelompok minoritas, sedangkan penafsiran MK mengarah kepada perlindungan mayoritas agama dari kesesatan paham minoritas. “Ini sangat aneh”, katanya. Masalah berikutnya, muncul dari pertanyaan tentang hubungan agama-negara: apakah Indonesia ingin menjadi negara modern yang rasional, ataukah menjadi agama negara?
Kalau sila pertama disebut sebagai bias monoteis, sila kelima dikritik Luthfi karena ia bias sosialis. Bagi Luthfi, sila kelima ini jadi bermasalah karena berkaitan dengan kebebasan ekonomi. Memposisikan diri sebagai seorang libertarian, Luthfi mengkritik istilah keadilan sosial yang baginya sangat rancu dan “sarat makna”. Keadilan, demikian Luthfi menguraikan, adalah terminologi yang datang dari filsafat dan agama. Karena itu, istilah keadilan menempati kedudukan yang sangat penting dalam ideologi negara. Tapi penisbatan keadilan dengan sosial, adalah retoris. Keadilan itu sendiri berhubungan dengan individu sebagai bentuk paripurna apa yang disebut sebagai minoritas. Ketika berbicara minoritas, berarti kita berbicara individu per individu. Keadilan yang sebenarnya seharusnya membuka kebebasan berusaha (ekonomi) yang seluas-luasnya kepada masing-masing individu. Demikian, karena kebebasan berusaha individu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi setiap bangsa.
Luthfi mencontohkan bagaimana negara-negara yang kebebasan berusaha atau economic freedom-nya tinggi biasanya menjadi negara yang makmur sejahtera. Sedangkan istilah keadilan sosial yang lebih menekankan aspek distribusi, dipandang bias sosialis. Secara logis, demikian Luthfi, adalah keliru ketika berbicara tentang distribusi kekayaan sementara kekayaan itu sendiri belum ada. Yang benar adalah bagaimana kekayaan itu diciptakan terlebih dulu melalui kebebasan ekonomi, baru kemudian kita bicara tentang distribusinya. Walaupun konsep ini tidak disetujui oleh umumnya negara-negara liberal, tapi cara demikian itu relatif berhasil dijalankan oleh negara-negara penganut sistem welfare-state. Bagi Luthfi, ukuran kebebasan ekonomi itu sederhana: yaitu apakah setiap individu itu bebas untuk bekerja, berusaha, memindahkan barang kemana saja ia suka; apakah ijin melakukan usaha itu mudah dan cepat, atau cenderung birokratis dan berbelit-belit?
Inilah kritik Luthfi terhadap sila ketuhanan dan sila keadilan. Bagi Luthfi, kalau sila ketuhanan yang melahirkan negara pancasila –sebagai sintesa antara negara sekuler dan negara agama– merupakan cerminan politik bangsa, maka sila keadilan yang melahirkan ekonomi pancasila –sebagai sintesa antara negara liberal dan sosialis– adalah cerminan kebijakan ekonomi negara kita. Kedua sintesa tersebut dalam pandangan Luthfi menyisakan sejumlah masalah. Dan karena ia bermasalah, maka konstitusi-konstitusi dan segenap Undang-Undang yang lahir dari dasar tersebut juga tidak lepas dari masalah-masalah. Dengan kondisi yang bermasalah itu, Luthfi menyebut Indonesia sebagai “negara-yang-bukan-bukan”: politiknya bukan-bukan dan ekonominya juga bukan-bukan.
Secara Khusus Luthfi mengkritik Yudi Latif dengan mengatakan tidak menemukan argumen kritis pada bukunya Negara Paripurna tersebut. Sebaliknya, buku Negara Paripurna malah melestarikan konsep “negara-yang-bukan-bukan” itu. Ketika menguraikan sila pertama misalnya, Yudi dengan tegas memujinya dengan menyebutnya sebagai pencapaian yang sangat progresif. Dan karena itu, Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekular. Sedangkan terkait sila kelima, Luthfi mengkritik buku ini karena menurutnya, Yudi terlalu beromantisasi dengan para founding fathers negara ini. Sambil menegaskan kekagumannya pada pendiri bangsa ini, diakhir uraiannya, Luthfi mengajukan dua solusi atas masalah ini. Pertama, dengan melakukan amandemen atas kedua sila yang bermasalah itu. Baginya, amandemen bukan suatu yang asing buat negara kita. Sepanjang sejarah, kita sudah berulang kali melakukan amandemen. Kedua, dengan memperebutkan makna atau tafsir dari kedua sila bermasalah itu. Luthfi mengingatkan, cara kedua ini sangat melelahkan, karena ia membutuhkan proses yang panjang dan menuntut kedewasaan bernegara dan beragama.
Yudi Latip yang malam itu agak datang terlambat, memberikan uraian dan tanggapan balik atas presentasi Luthfi. Ia mengutarakan keprihatinannya atas kondisi mutakhir perdebatan soal kenegaraan di negeri ini yang menurutnya tidak menunjukkan kecerdasan. Jika kita menarik memori ke belakang, terutama ketika sidang BPUPKI diselenggarakan, perdebatan seputar kenegaraan ketika itu begitu marak dan cerdas. Yudi sangat terkesan bagaimana tokoh-tokoh kemerdekaan ketika itu mengikutsertakan semua perwakilan yang merepresentasikan kelompok-kelompok dan golongan di Indonesia—sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam sejarah negara-negara Eropa dan Amerika sekalipun. Berbeda dengan Indonesia, Amerika baru belakangan saja memberikan hak pilih pada wanita, dan mengakui hak-hak kelompok di luar Anglo-Saxon. Dari sini, Yudi merasa perlu diagendakan kembali menghadirkan ulang perdebatan masa lalu itu.
Masuk ke dalam pembahasan ideologi Pancasila, Yudi melihat jarak antara perumusan konstitusi dengan pancasila tidak berselang lama. Keduanya bagi Yudi merupakan satu kesatuan paket. Tidak ada satu sila pun dalam pancasila yang tidak memiliki penjabarannya dalam konstitusi. Hubungan antara Pancasila dan konstitusi oleh Yudi dianalogikan sebagai hubungan antara al-Qur’an dan Hadis dalam rumusan legislasi Islam.
Terkait hubungan ini, setidaknya ada tiga poin yang sempat menjadi sasaran kritik Yudi. Pertama, Yudi menyesali ketiadaan ketentuan pembatasan masa jabatan presiden dalam UUD ‘45. Menurut Yudi, kesalahan ini terjadi karena pada waktu itu rumusan yang dibuat merujuk pada konstitusi presidensil Amerika yang belum memiliki batasan periode jabatan presiden. Kedua, sakralisasi atas UUD ’45 yang menghalangi amandemen atas UUD ‘45. Menurut Yudi, ini adalah tindakan yang konyol. Sakralisasi ini bisa dilawan dengan mengenali ide pokok UUD ‘45 dari teknikalnya. Ini penting, karena dengan begitu kita akan tahu aspek mana-mana dari pokok UUD ‘45 yang tetap dari teknikalnya yang bisa diamandemen. Ketiga, Yudi mengkritik kategorisasi ilmiah yang sering digunakan ilmuwan untuk mengenali kelompok nasionalis dari kelompok Islam. Menurut Yudi, kategori ini cenderung menyesatkan, karena kategori-kategori itu tidak selalu homogen. Yudi mencontohkan bagaimana Agus Salim dari kelompok Islam misalnya, dalam beberapa hal cenderung sekuler. Atau Husein Djayadiningrat dari kelompok sekuler, yang sempat mengusulkan kata bismillah untuk pembukaan UUD ‘45. Disamping itu, kelima sila yang dikenal itu, substansinya dirumuskan secara kompak oleh kedua belah pihak. Jadi, kata Yudi, jangan dikira bahwa sebagian sila merupakan usulan kelompok sekuler dan sebagian lainnya adalah usulan kelompok Islam.
Di akhir uraiannya, Yudi berharap agar buku Negara Paripurna yang disusunnya itu bisa menjadi titik tolak perdebatan dan membuka kembali wacana-wacana cerdas yang telah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Sejauh ini, Yudi melihat setidaknya ada tiga pola warga Indonesia memandang Pancasila. Pertama, mereka yang menilai Pancasila adalah sakti. Kedua, mereka yang memandang Pancasila secara sinis. Bagi kelompok ini, Pancasila tidak lebih dari “sampah”, karena tidak mampu lagi menjawab tantangan era global. Ketiga, kelompok tengah, yaitu mereka yang tidak men-sakti-kan Pancasila, tidak juga melihatnya sebagai “sampah”. Menurut kelompok yang terakhir ini, Pancasila perlu diberi isi, dalam artian sentuhan-sentuhan tafsir kontekstual terhadapnya.
Selesai presentasi dua narasumber, diskusi diteruskan sesi tanya jawab dengan peserta. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan dikomentari singkat oleh nara sumber. Bebarapa komentar penting misalnya pertanyaan pertama, mengenai perbandingan konstitusi di Indonesia dan Singapura. Luthfi mengomentari, baginya, indeks kebebasan ekonomi di Singapura lumayan bagus, namun sangat buruk dari segi kebebasan politik, berbanding terbalik dengan Indonesia. Pertanyaan kedua, mengenai gagasan amandemen pancasila yang dikhawatirkan justru akan membuka luka lama perdebatan sengit antara kelompok nasionalis dan Islam atau malah memberi kesempatan kepada kelompok ekstrimis Islam untuk mensyari’atkan negara. Atas pertanyaan, Luthfi mengatakan, ia juga memiliki kekhawatiran yang sama. Namun demikian Luthfi mengingatkan tentang watak kontekstual perumusan konstitusi UU. Ia mengandaikan para pendiri bangsa ketika itu mengerti perkembangan teknologi seperti sekarang ini, tentu rumusan pancasila akan berubah.
Pertanyaan ketiga, berupa sanggahan atas kritik Luthfi atas sila ke satu dan ke lima. Mengutip pandangan Nurcholish Madjid, tentang monoteisme yang benar tentu tidak menjadi ancaman, bahkan membuka ruang untuk ateisme. Terkait sila kelima, kenapa tidak menjadikannya sebagai jalan ketiga (third way) seperti diteorikan Giddens. Komentar Luthfi atas sanggahan ini, setiap generasi itu punya pandangan dan wawasan yang berbeda. Generasi cak Nur, begitu Luthfi, tidak mengetahui wawasan kekinian generasi berikutnya. Sedangkan tentang jalan ketiga, Luthfi mengiyakan bahwa sila kelima bisa menempati posisi itu. Masalahnya, sampai saat ini kita melihat kenyataan bahwa ia tidak mampu membawa kepada kondisi perekonomian yang lebih baik.
Sementara Yudi Latif lebih mengomentari tanggapan-tanggapan peserta secara garis besar. Setidaknya ada empat poin penjelasan penting dari Yudi. Pertama, Yudi mengingatkan bahwa ideologi Pancasila tidak muncul dari ruang vakum, dan karena itu ia menjadi sarat nilai. Kita tahu, bahwa sepanjang sejarah negeri ini, politik dan ekonominya tidak pernah sepi dari campur tangan asing. Kedua, Yudi mengkritik praktik kapitalisasi purba yang hingga kini masih sering digunakan. Kapitalisasi purba dilukiskan Yudi sebagai kapitalisasi yang mengumpulkan kekayaan dengan menghisap sumber daya negara lain. Dalam kasus indonesia misalnya, contoh bagus kapitalisasi purba ini adalah VOC. Ketiga, Yudi menggambarkan para pendiri bangsa ini sebagai orang-orang yang tidak begitu mengerti filsafat, tapi faham firasat. Ungkapan ini bukan sebagai ejekan, justru malah pujian. Dengan firasatnya itu, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh para pendiri bangsa ini selamat dari ekstremisme, dalam artian mengambil jalan yang aman walaupun cenderung kompromistis. Contoh yang paling baik adalah tentang hak individu, walaupun hak individu diakui tapi dalam konstitusi negara kita ia tetap memiliki fungsi sosial.
Yudi juga memuji firasat ini sebagai sebuah kearifan yang luar biasa yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Keempat, terkait dengan anggapan utopisme terhadap buku Negara Paripurna. Yudi menjelaskan bahwa keparipurnaan yang ia maksudkan adalah paripurna dari sisi-sisi keutamaannya. Yudi mengakui bahwa ketika menulis buku ini, ia memposisikan diri sebagai ideolog, dan bukan ahli sains politik. Dengan kesempurnaan dari sisi-sisi keutamaannya itu, ideologi Pancasila diharapkan bisa menjadi alat bercermin oleh siapa saja dan kapan saja, yang bisa memperlihatkan sisi-sisi kelebihan dan kelemahan setiap generasi bangsa ini. Terakhir, Yudi juga mengingatkan, seandainya ideal-ideal di dalamnya itu bisa didekati dalam level praktis, maka tujuan negara paripurna bukan tidak mungkin akan dicapai. []
http://islamlib.com/id/artikel/sila-pertama-dan-sila-terakhir-pancasila-bermasalah
Setelah kurang lebih off dua bulan, diskusi rutin bulanan Jaringan Islam Liberal (JIL) kembali hadir, kamis (25 Mei 2011). Diskusi bulanan kali pertama JIL semenjak mendapat ancaman bom beberapa waktu lalu ini mengambil tema “Indonesia dan Doktrin Pancasila”, dengan menghadirkan dua orang pembicara: Luthfi Assyaukanie (JIL) dan Yudi Latif (Reform Institute). Secara khusus, tema diskusi kali ini terkait dengan buku terbaru Yudi Latif berjudul Negara Paripurna.
Luthfi Assyaukanie mengawali diskusi dengan bercerita tentang kegiatan peluncuran buku Negara Paripurna beberapa waktu lalu yang sempat ia hadiri. Ia takjub dengan meriahnya ucapan selamat yang diberikan orang atas peluncuran buku ini. “Ucapan selamat untuk buku Yudi Latif ini melebihi ucapan selamat untuk sebuah pernikahan,” katanya.
Apresiasi besar terhadap buku ini, bagi Luthfi, tidak lepas dari konteks mutakhir keindonesiaan yang mem-flashback memori kita ke masa lalu, di mana ancaman terhadap pancasila dan kebebasan beragama kembali terjadi. Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif ini tepat sekali hadir dalam kondisi demikian, dan karenanya wajar jika banyak apresiasi ditujukan kepadanya. Luthfi mengutip ucapan politikus kenamaan PDIP, Taufik Kiemas, yang juga sempat hadir dalam peluncuran buku saat itu: “Inilah buku yang bisa menjadi rujukan kita di tengah kondisi di mana ancaman terhadap pancasila dan kebebasan beragama terulang lagi,” katanya.
Banyaknya pujian atas buku Negara Paripurna, mendorong Luthfi untuk ikut memberikan komentar dan juga kritik atas buku tersebut. Dari judulnya saja, kata Luthfi, penulis buku ini seolah ingin memposisikan diri sebagai Plato dengan negara idam-idamannya, Repubik; atau Al-Farabi dengan al-Madinah al-Fadlilah-nya. Bagi Luthfi, semua konsep negara ideal, seperti dicita-citakan baik oleh Plato, Al- Farabi, dan sekarang oleh Yudi Latif dengan Negara Paripurna-nya itu, merupakan konsep yang utopis, dalam artian tidak realistis, mengawang-awang dan karenanya menjadi sulit untuk diterapkan.
Luthfi juga mengkritik buku ini yang menurutnya terlalu kental nuansa filsafat politiknya. Ia menyarankan, seandainya ditambahkan sedikit saja sentuhan political sciencies, buku ini akan lebih istimewa. Bukan hanya berbicara tentang teori demokrasi misalnya, tapi bagaimana caranya demokrasi itu bisa diterapkan di Indonesia. Namun demikian, Luthfi mengakui ada yang baru dari buku Negara Paripurna Yudi Latif ini. Luthfi terkesan dengan metode penyajian buku ini yang menurutnya mirip dengan tafsir-tafsir klasik, seperti tafsir Al-Thabari misalnya, yang membahas poin-poin secara berurutan. Seperti halnya tafsir-tafsir itu, buku Yudi Latif juga menyajikan bahasan sila-sila dalam pancasila secara berurutan ditambah dengan prolog dan penutup. Pada setiap bahasan sila, dijelaskan alasan posisi urutan sila tersebut, latar belakang kenapa suatu sila itu muncul dan juga wording-nya. Bandingkan dengan tafsir-tafsir klasik yang membahas ayat-ayat secara berurutan dengan menjelaskan munasabah, asbabunnuzul dan mufradat-nya.
Ada banyak buku di dunia ini yang membicarakan masalah Pancasila dalam pelbagai bahasa, dari mulai Indonesia, Inggris dan sebagainya. Jika kita merujuk kepada perpustakaan kongres di Amerika Serikat saja misalnya, kita akan menemukan buku-buku bertema pancasila tidak kurang dari 600-an judul buku, dan buku karya Yudi Latif ini salah satu dari sekian banyak buku tersebut. Banyaknya buku bertema Pancasila menurut Luthfi, merupakan salah satu indikasi bahwa bahasan tentang tema tersebut begitu penting. Hal demikian dapat dipahami, mengingat Pancasila sebagai sebuah ideologi tunggal negara, dihadapkan oleh banyak ideologi lain yang menjadi saingannya. Di sini, kita dihadapkan oleh persaingan ideologi.
Jika merujuk kepada sejarah konsolidasi Pancasila misalnya, menurut teori Deliar Noer yang mengkategorikan kelompok-kelompok perumus Pancasila menjadi muslim- nasionalis dan nasionalis-sekuler, persaingan ketat antar ideologi ketika itu begitu sengit terjadi. Perdebatan ideologi yang paling sengit ketika itu terjadi antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler. Konflik dengan ideologi sosialisme-komunisme juga ada, tapi tidak begitu berarti. Pancasila lahir justru dari persaingan antara dua kelompok tersebut, yang belakangan melahirkan kompromi dalam bentuknya yang sekarang kita kenal. Uniknya, pancasila sebagai kompromi tidak memberikan kepuasan antara kedua kelompok, baik kelompok islamis maupun nasionalis sekuler. Sebaliknya, kedua kelompok itu justru merasa dikecewakan. Ini menjelaskan mengapa hingga kini rongrongan-rongrongan terhadap pancasila terus berdatangan terutama dari kelompok islamis. Terkait ini Luthfi menegaskan, kalaupun ada yang harus kecewa dan dirugikan, justru kelompok nasionalis sekuler-lah yang semestinya merasakan itu, mengingat terlalu besar pengorbanan mereka untuk sampai pada kompromi tersebut.
Dari kritik atas buku Yudi Latif, Luthfi berangkat lebih jauh kepada kritik pancasila sebagai ideologi negara. Luthfi merasa bahwa ada yang salah dengan konstitusi negara kita, khususnya dalam rumusan Pancasila. Sebelum melontarkan kritik, Luthfi dengan santun juga mengingatkan, mungkin kritiknya ini akan dibilang simplifikasi atau mungkin juga “kurang ajar”. Namun begitu, ia berpendapat bahwa sebagai kritik akademis, hal itu wajar belaka. Luthfi memandang dari lima rumusan pancasila, ada dua sila yang bermasalah, yaitu sila pertama (tentang ketuhanan) dan terakhir (tentang keadilan). Tiga sila lebihnya, baginya relatif tidak bermasalah, karena “konsep-negara-modern” bisa menerima itu. Berbeda dengan tiga sila itu, sila pertama yang merupakan representasi landasan ideologi politik, dan sila kelima yang merepresentasikan landasan ideologi ekonomi, bagi Luthfi cenderung rancu dan kacau.
Menjelaskan argumennya atas kritik sila pertama, Luthfi mengatakan, landasan filosofis sangat penting untuk etika bernegara dan bermasyarakat, dan karenanya rumusan yang rasional menjadi sangat penting untuk sebuah konstitusi. Luthfi memberikan contoh betapa buruknya retorika kelompok Islam dalam sejarah ketika mendebatkan sila pertama ini. Kelompok Islam yang ketika itu kalah berargumentasi secara filosofis dengan kelompok nasionalis-sekuler, menunjukkan perilaku yang cenderung tidak objektif (kasus Kasman Singodimejo yang memukul meja karena emosional). Suasana ketika itu bisa dilukiskan betapa kuatnya tekanan kelompok Islam atas sila pertama ini. Ini dibuktikan setidaknya oleh dua hal. Pertama, pemindahan urutan sila dari terakhir menjadi pertama. Kedua, perubahan redaksi rumusan sila ketuhanan, dari ketuhanan yang berkebudayaan seperti dirumuskan Soekarno, menjadi ketuhanan yang maha esa seperti kita kenal sekarang.
Luthfi menyangsikan apakah rumusan sila ketuhanan tersebut akan mampu melewati sejarah, mengingat dalam perjalanannya rumusan demikian itu menyisakan banyak sekali persoalan. Keraguan Luthfi bukannya tanpa alasan. Ia melihat sila pertama ini sangat bias monoteisme. Dengan ideologi yang bias monoteis tersebut, Luthfi menyangsikan apakah Budha dan Hindu misalnya, bisa diterima “secara ikhlas” di negeri ini. Belum lagi fenomena ateisme dan agnostisisme yang belakangan fenomenanya muncul kepermukaan (terkait niat asosiasi kelompok ateisme indonesia yang berniat menyusun buku bertajuk: Apakah Ateisme Dapat Hidup di Indonesia?). Dengan konstitusi yang bias monoteis itu, Luthfi menyangsikan apakah ateisme itu punya prospek legal di Indonesia. Dengan tafsir yang berbeda, seperti pemahaman Buya Syafi’i Ma’arif misalnya, sila pertama memang bisa membuka ruang untuk ateisme. Pertanyaannya: apakah penafsiran seperti itu bisa diterima dikhalayak luas? Jika itu tetap dipertahankan, maka kemungkinannya kita harus bertarung memperebutkan makna dan itu berarti akan sangat melelahkan.
Luthfi juga mengingatkan bahayanya asosiasi agama yang berlebihan terhadap negara, karena bisa melahirkan beberapa masalah. Pertama, konsekuensi penyatuan ideologi agama dan negara dalam kehidupan sosial-politik-keagamaan kita. Lihat misalnya kasus-kasus institusionalisasi agama oleh negara, seperti MUI, Departemen Agama, dan sebagainya. Dengan asosiasi berlebih kepada agama ini, negara juga menjadi terbebani secara moral untuk melindungi institusi-institusi agama tersebut.
Ketika agama dikooptasi oleh negara, maka implikasinya adalah lahirnya diskriminasi mayoritas terhadap minoritas. Luthfi mencontohkan bagiamana sulitnya ia berdebat di Mahkamah Konstitusi ketika membela kelompok minoritas Ahmadiah misalnya. Dalam hal ini, baik Luthfi dan pihak MK sama-sama setuju bahwa negara berkewajiban melindungi agama. Bedanya pembelaan Luthfi mengarah kepada perlindungan agama kepada kelompok minoritas, sedangkan penafsiran MK mengarah kepada perlindungan mayoritas agama dari kesesatan paham minoritas. “Ini sangat aneh”, katanya. Masalah berikutnya, muncul dari pertanyaan tentang hubungan agama-negara: apakah Indonesia ingin menjadi negara modern yang rasional, ataukah menjadi agama negara?
Kalau sila pertama disebut sebagai bias monoteis, sila kelima dikritik Luthfi karena ia bias sosialis. Bagi Luthfi, sila kelima ini jadi bermasalah karena berkaitan dengan kebebasan ekonomi. Memposisikan diri sebagai seorang libertarian, Luthfi mengkritik istilah keadilan sosial yang baginya sangat rancu dan “sarat makna”. Keadilan, demikian Luthfi menguraikan, adalah terminologi yang datang dari filsafat dan agama. Karena itu, istilah keadilan menempati kedudukan yang sangat penting dalam ideologi negara. Tapi penisbatan keadilan dengan sosial, adalah retoris. Keadilan itu sendiri berhubungan dengan individu sebagai bentuk paripurna apa yang disebut sebagai minoritas. Ketika berbicara minoritas, berarti kita berbicara individu per individu. Keadilan yang sebenarnya seharusnya membuka kebebasan berusaha (ekonomi) yang seluas-luasnya kepada masing-masing individu. Demikian, karena kebebasan berusaha individu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi setiap bangsa.
Luthfi mencontohkan bagaimana negara-negara yang kebebasan berusaha atau economic freedom-nya tinggi biasanya menjadi negara yang makmur sejahtera. Sedangkan istilah keadilan sosial yang lebih menekankan aspek distribusi, dipandang bias sosialis. Secara logis, demikian Luthfi, adalah keliru ketika berbicara tentang distribusi kekayaan sementara kekayaan itu sendiri belum ada. Yang benar adalah bagaimana kekayaan itu diciptakan terlebih dulu melalui kebebasan ekonomi, baru kemudian kita bicara tentang distribusinya. Walaupun konsep ini tidak disetujui oleh umumnya negara-negara liberal, tapi cara demikian itu relatif berhasil dijalankan oleh negara-negara penganut sistem welfare-state. Bagi Luthfi, ukuran kebebasan ekonomi itu sederhana: yaitu apakah setiap individu itu bebas untuk bekerja, berusaha, memindahkan barang kemana saja ia suka; apakah ijin melakukan usaha itu mudah dan cepat, atau cenderung birokratis dan berbelit-belit?
Inilah kritik Luthfi terhadap sila ketuhanan dan sila keadilan. Bagi Luthfi, kalau sila ketuhanan yang melahirkan negara pancasila –sebagai sintesa antara negara sekuler dan negara agama– merupakan cerminan politik bangsa, maka sila keadilan yang melahirkan ekonomi pancasila –sebagai sintesa antara negara liberal dan sosialis– adalah cerminan kebijakan ekonomi negara kita. Kedua sintesa tersebut dalam pandangan Luthfi menyisakan sejumlah masalah. Dan karena ia bermasalah, maka konstitusi-konstitusi dan segenap Undang-Undang yang lahir dari dasar tersebut juga tidak lepas dari masalah-masalah. Dengan kondisi yang bermasalah itu, Luthfi menyebut Indonesia sebagai “negara-yang-bukan-bukan”: politiknya bukan-bukan dan ekonominya juga bukan-bukan.
Secara Khusus Luthfi mengkritik Yudi Latif dengan mengatakan tidak menemukan argumen kritis pada bukunya Negara Paripurna tersebut. Sebaliknya, buku Negara Paripurna malah melestarikan konsep “negara-yang-bukan-bukan” itu. Ketika menguraikan sila pertama misalnya, Yudi dengan tegas memujinya dengan menyebutnya sebagai pencapaian yang sangat progresif. Dan karena itu, Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekular. Sedangkan terkait sila kelima, Luthfi mengkritik buku ini karena menurutnya, Yudi terlalu beromantisasi dengan para founding fathers negara ini. Sambil menegaskan kekagumannya pada pendiri bangsa ini, diakhir uraiannya, Luthfi mengajukan dua solusi atas masalah ini. Pertama, dengan melakukan amandemen atas kedua sila yang bermasalah itu. Baginya, amandemen bukan suatu yang asing buat negara kita. Sepanjang sejarah, kita sudah berulang kali melakukan amandemen. Kedua, dengan memperebutkan makna atau tafsir dari kedua sila bermasalah itu. Luthfi mengingatkan, cara kedua ini sangat melelahkan, karena ia membutuhkan proses yang panjang dan menuntut kedewasaan bernegara dan beragama.
Yudi Latip yang malam itu agak datang terlambat, memberikan uraian dan tanggapan balik atas presentasi Luthfi. Ia mengutarakan keprihatinannya atas kondisi mutakhir perdebatan soal kenegaraan di negeri ini yang menurutnya tidak menunjukkan kecerdasan. Jika kita menarik memori ke belakang, terutama ketika sidang BPUPKI diselenggarakan, perdebatan seputar kenegaraan ketika itu begitu marak dan cerdas. Yudi sangat terkesan bagaimana tokoh-tokoh kemerdekaan ketika itu mengikutsertakan semua perwakilan yang merepresentasikan kelompok-kelompok dan golongan di Indonesia—sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam sejarah negara-negara Eropa dan Amerika sekalipun. Berbeda dengan Indonesia, Amerika baru belakangan saja memberikan hak pilih pada wanita, dan mengakui hak-hak kelompok di luar Anglo-Saxon. Dari sini, Yudi merasa perlu diagendakan kembali menghadirkan ulang perdebatan masa lalu itu.
Masuk ke dalam pembahasan ideologi Pancasila, Yudi melihat jarak antara perumusan konstitusi dengan pancasila tidak berselang lama. Keduanya bagi Yudi merupakan satu kesatuan paket. Tidak ada satu sila pun dalam pancasila yang tidak memiliki penjabarannya dalam konstitusi. Hubungan antara Pancasila dan konstitusi oleh Yudi dianalogikan sebagai hubungan antara al-Qur’an dan Hadis dalam rumusan legislasi Islam.
Terkait hubungan ini, setidaknya ada tiga poin yang sempat menjadi sasaran kritik Yudi. Pertama, Yudi menyesali ketiadaan ketentuan pembatasan masa jabatan presiden dalam UUD ‘45. Menurut Yudi, kesalahan ini terjadi karena pada waktu itu rumusan yang dibuat merujuk pada konstitusi presidensil Amerika yang belum memiliki batasan periode jabatan presiden. Kedua, sakralisasi atas UUD ’45 yang menghalangi amandemen atas UUD ‘45. Menurut Yudi, ini adalah tindakan yang konyol. Sakralisasi ini bisa dilawan dengan mengenali ide pokok UUD ‘45 dari teknikalnya. Ini penting, karena dengan begitu kita akan tahu aspek mana-mana dari pokok UUD ‘45 yang tetap dari teknikalnya yang bisa diamandemen. Ketiga, Yudi mengkritik kategorisasi ilmiah yang sering digunakan ilmuwan untuk mengenali kelompok nasionalis dari kelompok Islam. Menurut Yudi, kategori ini cenderung menyesatkan, karena kategori-kategori itu tidak selalu homogen. Yudi mencontohkan bagaimana Agus Salim dari kelompok Islam misalnya, dalam beberapa hal cenderung sekuler. Atau Husein Djayadiningrat dari kelompok sekuler, yang sempat mengusulkan kata bismillah untuk pembukaan UUD ‘45. Disamping itu, kelima sila yang dikenal itu, substansinya dirumuskan secara kompak oleh kedua belah pihak. Jadi, kata Yudi, jangan dikira bahwa sebagian sila merupakan usulan kelompok sekuler dan sebagian lainnya adalah usulan kelompok Islam.
Di akhir uraiannya, Yudi berharap agar buku Negara Paripurna yang disusunnya itu bisa menjadi titik tolak perdebatan dan membuka kembali wacana-wacana cerdas yang telah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Sejauh ini, Yudi melihat setidaknya ada tiga pola warga Indonesia memandang Pancasila. Pertama, mereka yang menilai Pancasila adalah sakti. Kedua, mereka yang memandang Pancasila secara sinis. Bagi kelompok ini, Pancasila tidak lebih dari “sampah”, karena tidak mampu lagi menjawab tantangan era global. Ketiga, kelompok tengah, yaitu mereka yang tidak men-sakti-kan Pancasila, tidak juga melihatnya sebagai “sampah”. Menurut kelompok yang terakhir ini, Pancasila perlu diberi isi, dalam artian sentuhan-sentuhan tafsir kontekstual terhadapnya.
Selesai presentasi dua narasumber, diskusi diteruskan sesi tanya jawab dengan peserta. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan dikomentari singkat oleh nara sumber. Bebarapa komentar penting misalnya pertanyaan pertama, mengenai perbandingan konstitusi di Indonesia dan Singapura. Luthfi mengomentari, baginya, indeks kebebasan ekonomi di Singapura lumayan bagus, namun sangat buruk dari segi kebebasan politik, berbanding terbalik dengan Indonesia. Pertanyaan kedua, mengenai gagasan amandemen pancasila yang dikhawatirkan justru akan membuka luka lama perdebatan sengit antara kelompok nasionalis dan Islam atau malah memberi kesempatan kepada kelompok ekstrimis Islam untuk mensyari’atkan negara. Atas pertanyaan, Luthfi mengatakan, ia juga memiliki kekhawatiran yang sama. Namun demikian Luthfi mengingatkan tentang watak kontekstual perumusan konstitusi UU. Ia mengandaikan para pendiri bangsa ketika itu mengerti perkembangan teknologi seperti sekarang ini, tentu rumusan pancasila akan berubah.
Pertanyaan ketiga, berupa sanggahan atas kritik Luthfi atas sila ke satu dan ke lima. Mengutip pandangan Nurcholish Madjid, tentang monoteisme yang benar tentu tidak menjadi ancaman, bahkan membuka ruang untuk ateisme. Terkait sila kelima, kenapa tidak menjadikannya sebagai jalan ketiga (third way) seperti diteorikan Giddens. Komentar Luthfi atas sanggahan ini, setiap generasi itu punya pandangan dan wawasan yang berbeda. Generasi cak Nur, begitu Luthfi, tidak mengetahui wawasan kekinian generasi berikutnya. Sedangkan tentang jalan ketiga, Luthfi mengiyakan bahwa sila kelima bisa menempati posisi itu. Masalahnya, sampai saat ini kita melihat kenyataan bahwa ia tidak mampu membawa kepada kondisi perekonomian yang lebih baik.
Sementara Yudi Latif lebih mengomentari tanggapan-tanggapan peserta secara garis besar. Setidaknya ada empat poin penjelasan penting dari Yudi. Pertama, Yudi mengingatkan bahwa ideologi Pancasila tidak muncul dari ruang vakum, dan karena itu ia menjadi sarat nilai. Kita tahu, bahwa sepanjang sejarah negeri ini, politik dan ekonominya tidak pernah sepi dari campur tangan asing. Kedua, Yudi mengkritik praktik kapitalisasi purba yang hingga kini masih sering digunakan. Kapitalisasi purba dilukiskan Yudi sebagai kapitalisasi yang mengumpulkan kekayaan dengan menghisap sumber daya negara lain. Dalam kasus indonesia misalnya, contoh bagus kapitalisasi purba ini adalah VOC. Ketiga, Yudi menggambarkan para pendiri bangsa ini sebagai orang-orang yang tidak begitu mengerti filsafat, tapi faham firasat. Ungkapan ini bukan sebagai ejekan, justru malah pujian. Dengan firasatnya itu, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh para pendiri bangsa ini selamat dari ekstremisme, dalam artian mengambil jalan yang aman walaupun cenderung kompromistis. Contoh yang paling baik adalah tentang hak individu, walaupun hak individu diakui tapi dalam konstitusi negara kita ia tetap memiliki fungsi sosial.
Yudi juga memuji firasat ini sebagai sebuah kearifan yang luar biasa yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Keempat, terkait dengan anggapan utopisme terhadap buku Negara Paripurna. Yudi menjelaskan bahwa keparipurnaan yang ia maksudkan adalah paripurna dari sisi-sisi keutamaannya. Yudi mengakui bahwa ketika menulis buku ini, ia memposisikan diri sebagai ideolog, dan bukan ahli sains politik. Dengan kesempurnaan dari sisi-sisi keutamaannya itu, ideologi Pancasila diharapkan bisa menjadi alat bercermin oleh siapa saja dan kapan saja, yang bisa memperlihatkan sisi-sisi kelebihan dan kelemahan setiap generasi bangsa ini. Terakhir, Yudi juga mengingatkan, seandainya ideal-ideal di dalamnya itu bisa didekati dalam level praktis, maka tujuan negara paripurna bukan tidak mungkin akan dicapai. []
http://islamlib.com/id/artikel/sila-pertama-dan-sila-terakhir-pancasila-bermasalah
Pseudo Toleransi: Metode Dakwah al-Qardlawi dan Masa Depan Pluralisme
Oleh : Prio Hotman, MA
“…..jika dikatakan bahwa arti pluralisme agama (al-ta’addudiyyah al-diniyyah) adalah semua agama itu benar (haq), dan pendapat ini menurut kami tidak benar, maka pluralisme agama yang sesungguhnya adalah menegaskan bahwa sesungguhnya agamaku adalah yang benar, dan agama orang lain adalah salah (bathil). Meski demikian, mereka berhak untuk hidup dan kita boleh bergaul dengan mereka demi kebaikan. Dan hak kita juga untuk berdamai dengan mereka yang mengajak berdamai, dan berperang dengan mereka yang mengajak berperang. Dan karena kami meyakini bahwa agama orang lain salah, maka menjadi hak kami untuk berdakwah, mengajak mereka untuk masuk agama kami…”.
Kutipan di atas adalah pernyataan ulama sohor Syeikh Yusuf al-Qardlawi, sebagaimana dilansir dalam sebuah situs Islam online (lihat http://www.alwihdah.com/news/news/2010-04-26-741.htm). Sosok Yusuf al-Qardlawi, dikenal sebagai ulama yang kontroversial, bukan hanya bagi kelompok konservatif, tapi juga oleh kelompok liberal. Dari pandangan konservatif, al-Qardlawi dijuluki sebagai ahli fikih yang ingkar sunnah. Dan dari sudut kelompok liberal, al- Qardlawi tidak lebih dari seorang konservatif yang “pura-pura” modern. Menurut Luthfi Assaukanie (2007: 180), pemikiran al-Qardlawi ini di Indonesia direpresentasikan oleh ulama-ulama yang mengaku moderat, tapi pada saat yang sama merangkul pandangan-pandangan konservatif, semisal ulama-ulama yang berada di jajaran MUI. Ulama-ulama di MUI dan yang sepandangan dengan mereka memang mendakwahkan toleransi antar umat beragama, tenggang rasa, dan menghormati kebhinekaan. Tapi pada saat bersamaan mereka juga mengharamkan pluralisme dan menyesatkan Ahmadiyah.
Belakangan ketika fenomena kekerasan beragama marak terjadi, KH. Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU, dalam beberapa kesempatan dialog di televisi swasta, mengeluarkan statemen yang agak rancu. Menurutnya, deradikalisasi terorisme hanya bisa diatasi dengan pluralisme sosial, bukan pluralisme teologis. Tampak sekali di sini bahwa pandangan Hasyim Muzadi tidak lebih baik dari pernyataan ulama-ulama MUI yang menerima pluralitas tapi mengharamkan pluralisme.
Jika ditelisik lebih jauh, toleransi yang didakwahkan oleh al-Qardlawi, Hasyim Muzadi dan ulama-ulama MUI, sebetulnya tidak lebih dari respon terhadap desakan fakta sosiologis kondisi umat yang dipandang makin radikal. Karena sifatnya desakan, maka toleransi demikian terkesan kompromistis. Ada satu dogma yang ingin dipertahankan dalam kerangka toleransi versi al-Qardlawi dkk. yang demikian, yakni dogma tentang monopoli klaim kebenaran (truth claim). Saya ingin menyebut toleransi ala mereka itu sebagai “pseudo tolerance” atau “toleransi seolah-olah”. Toleransi yang demikian adalah konsep toleransi yang setengah-setengah, penuh kompromi dan tidak didasari oleh niat yang utuh. Di satu sisi, mereka dipaksa untuk mengakui dan bergaul dengan realitas yang tidak tunggal, tapi di sisi yang lain mereka enggan untuk membuang pandangan-pandangan eksklusif dalam keberagamaannya.
Karena itu, model toleransi demikian ini hanya sebatas kulit saja dan tidak memiliki akar yang kuat sebagai landasan pergaulan masyarakat global yang multikultural. Sebab di bawah sadar, ia masih menyisakan potensi kekerasan dalam wujud klaim-klaim kebenaran beragama. Dalam paradigma pseudo toleransi ini, pokok soal tentang kebenaran tunggal iman menjadi tema sentral dan absolut. Orang yang menganut model toleransi demikian, biasanya masih bernafsu atau mengincar umat beragama lain untuk dikonversi ke dalam agamanya.
Para penganut pseudo toleransi sangat sulit melepaskan diri dari sikap eksklusivisme beragama. Mereka pada umumnya mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Agama lain, menurut mereka, jikapun itu pernah diwahyukan Allah kepada para nabi-Nya, tapi belakangan keabsahannya sudah terwakilkan (baca: di-mansukh, diabrogasi) oleh agama Islam. Karena itu, siapa yang masih menganut agama di luar Islam setelah mendengar kebenaran dakwah Islam, maka keyakinannya itu tertolak dan ia tidak akan selamat di akhirat. Mereka sebetulnya mengakui bahwa sebagian dari keputusan Allah (sunnatullah) terhadap manusia adalah menjadikannya tidak satu agama. Mereka juga mengakui bahwa setiap usaha kepada homogenisasi agama adalah usaha yang sia-sia. Namun begitu, mereka juga bersikeras bahwa Islam telah menghapus kebenaran agama-agama sebelumnya berdasarkan ayat Qur’an dalam surat al-Baqarah (2: 106): “Dan ayat mana saja yang kami nasakh-kan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya.”
Pandangan Muhammad al-Ghazali –seorang tokoh Ikhwan Mesir– dalam buku al-Ta’asshub wa al-Tasâmuh bain al-Masîhiyyah wa al-Islâm (Fanatisme dan Toleransi antara Islam dan Kristen [2005: 70]) mewakili paradigma pseudo toleransi ini. Ulama tersebut menganalogikannya dengan dokter yang menyarankan makanan berupa ASI untuk bayi pada awal periode kehidupannya. Saat beranjak besar kemudian ASI itu digantikan dengan makanan yang lembut, dan ketika dewasa semua makanan itu diganti dengan makanan yang lebih baik dan sempurna. Analog dengan agama yang terus mengalami revisi di mana versi terakhir adalah yang terbaik.
Dengan konsep toleransi yang semu ini, jangankan mendakwahkan keberagamaan yang inklusif, eksklusivisme beragamapun bahkan menjadi sangat sulit untuk dihidari. Bagaimana mungkin seorang yang meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bisa membiarkan penganut agama lain hidup tenang dengan keyakinannya. Orang yang menganut paham pseudo toleransi seperti ini tidak akan pernah bisa benar-benar toleransi. Yang ia bisa hanya pura-pura toleransi. Dikatakan begitu, karena ia tidak akan berhenti mencari-cari kesempatan kapan waktunya mengkonversi keyakinan orang lain itu ke dalam Islam.
Rumusan dakwah kepada non muslim, bagi para penganut pseudo toleransi, adalah “mengajak umat manusia untuk masuk Islam, dan jika mereka menerima itu, barulah mereka disuruh untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemunkaran.” Demikian seperti dikutip dari buku Hidâyat al Mursyidin (1979: 17) karya Syeikh Ali Mahfuz, seorang da’i kondang dari al-Azhar. Karena dasarnya yang rapuh, maka model toleransi ini alih-alih menjadi solusi pluralitas sosial, yang ada justru rentan sekali menyuburkan radikalisme dan fundamentalisme beragama. Bagaimanapun juga, eksklusivisme beragama tidak akan pernah melahirkan toleransi. Sebaliknya eksklusivisme justru melegitimasi radikalisme dan segala bentuk kekerasan beragama.
Pengakuan terhadap realitas mengharuskan pembenaran terhadap realitas itu sendiri. Dengan kata lain, pengakuan terhadap pluralitas berimplikasi pada pengakuan terhadap pluralisme. Jarak antara pluralitas dan pluralisme tidak berbeda dengan das sein dan das solen, antara yang senyatanya dan yang seharusnya. Seseorang tidak akan pernah bisa menerima kenyataan pluralitas dengan tulus, selama ia masih bersikeras menolak pluralisme. Dengan demikian, rumusan KH. Hasyim Muzadi tentang bolehnya menerima pluralisme sosial tapi wajib menolak pluralisme teologis seperti dipaparkan di atas, menjadi tidak relevan. Jika yang dimaksud beliau dengan pluralisme sosial adalah sikap menerima pluralitas sosial dengan cara toleransi dan bergaul dengan akur dan damai, maka yakinlah cita-cita dakwah demikian ini dapat dipastikan tidak akan kesampaian tanpa pengakuan pluralisme teologis yang menegaskan bahwa setiap agama itu adalah benar. Karena itu, mendakwahkan toleransi yang benar tidak akan bisa terwujud selama klaim-klaim kebenaran atau eksklusivisme itu masih bersikeras dipertahankan. Sebaliknya, mendakwahkan toleransi yang masih menyisakan ruang truth claim dan eksklusivisme hanya akan melahirkan toleransi-toleransi yang “hangat-hangat tahi ayam”: laris dan populer ketika banyak terjadi konflik dan kekerasan, tapi menghilang ketika suasana relatif stabil. Dengan kata lain, pseudo toleransi tidak akan pernah benar-benar utuh dan memadai untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan, tapi bersifat sebatas tambal sulam.
Sebagai garda terdepan umat muslim, sudah saatnya para ulama sekarang ini mengubah paradigmanya tentang toleransi. Sudah saatnya beralih dari pseudo toleransi atau toleransi yang setengah-setengah, kepada toleransi yang sejati. Toleransi sejati (al tasamuh al-haqîqiy) adalah toleransi yang lahir dari pola berpikir pluralisme, yaitu toleransi yang berani menyatakan bahwa bukan hanya agama saya saja yang benar, tetapi agama orang lain juga benar. Jika semua orang menjalankan agamanya masing-masing dengan sebenar-benarnya, maka sudah pasti akan melahirkan kedamaian, ketentraman hidup dan kerjasama sosial yang sehat.
Toleransi dan pluralisme tidak perlu disikapi sebagai ancaman akidah, karena setiap orang memiliki preferensinya sendiri-sendiri. Sebagaimana baju yang saya pakai, belum tentu nyaman dipakai oleh orang lain. Berdakwah kepada non muslim dalam rumusan ini, tidak lagi identik dengan mengkonversi iman mereka, tapi cukup mengajak mereka melakukan kerjasama sosial yang sehat. Inilah toleransi yang benar dan sehat, yang semestinya dijadikan rujukan dakwah oleh para da’i dan ulama-ulama di nusantara.
Wallahu a’lam bi al-shawab.
di muat di
http://islamlib.com/id/artikel/pseudo-toleransi-metode-dakwah-al-qardlawi-dan-masa-depan-pluralisme
“…..jika dikatakan bahwa arti pluralisme agama (al-ta’addudiyyah al-diniyyah) adalah semua agama itu benar (haq), dan pendapat ini menurut kami tidak benar, maka pluralisme agama yang sesungguhnya adalah menegaskan bahwa sesungguhnya agamaku adalah yang benar, dan agama orang lain adalah salah (bathil). Meski demikian, mereka berhak untuk hidup dan kita boleh bergaul dengan mereka demi kebaikan. Dan hak kita juga untuk berdamai dengan mereka yang mengajak berdamai, dan berperang dengan mereka yang mengajak berperang. Dan karena kami meyakini bahwa agama orang lain salah, maka menjadi hak kami untuk berdakwah, mengajak mereka untuk masuk agama kami…”.
Kutipan di atas adalah pernyataan ulama sohor Syeikh Yusuf al-Qardlawi, sebagaimana dilansir dalam sebuah situs Islam online (lihat http://www.alwihdah.com/news/news/2010-04-26-741.htm). Sosok Yusuf al-Qardlawi, dikenal sebagai ulama yang kontroversial, bukan hanya bagi kelompok konservatif, tapi juga oleh kelompok liberal. Dari pandangan konservatif, al-Qardlawi dijuluki sebagai ahli fikih yang ingkar sunnah. Dan dari sudut kelompok liberal, al- Qardlawi tidak lebih dari seorang konservatif yang “pura-pura” modern. Menurut Luthfi Assaukanie (2007: 180), pemikiran al-Qardlawi ini di Indonesia direpresentasikan oleh ulama-ulama yang mengaku moderat, tapi pada saat yang sama merangkul pandangan-pandangan konservatif, semisal ulama-ulama yang berada di jajaran MUI. Ulama-ulama di MUI dan yang sepandangan dengan mereka memang mendakwahkan toleransi antar umat beragama, tenggang rasa, dan menghormati kebhinekaan. Tapi pada saat bersamaan mereka juga mengharamkan pluralisme dan menyesatkan Ahmadiyah.
Belakangan ketika fenomena kekerasan beragama marak terjadi, KH. Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU, dalam beberapa kesempatan dialog di televisi swasta, mengeluarkan statemen yang agak rancu. Menurutnya, deradikalisasi terorisme hanya bisa diatasi dengan pluralisme sosial, bukan pluralisme teologis. Tampak sekali di sini bahwa pandangan Hasyim Muzadi tidak lebih baik dari pernyataan ulama-ulama MUI yang menerima pluralitas tapi mengharamkan pluralisme.
Jika ditelisik lebih jauh, toleransi yang didakwahkan oleh al-Qardlawi, Hasyim Muzadi dan ulama-ulama MUI, sebetulnya tidak lebih dari respon terhadap desakan fakta sosiologis kondisi umat yang dipandang makin radikal. Karena sifatnya desakan, maka toleransi demikian terkesan kompromistis. Ada satu dogma yang ingin dipertahankan dalam kerangka toleransi versi al-Qardlawi dkk. yang demikian, yakni dogma tentang monopoli klaim kebenaran (truth claim). Saya ingin menyebut toleransi ala mereka itu sebagai “pseudo tolerance” atau “toleransi seolah-olah”. Toleransi yang demikian adalah konsep toleransi yang setengah-setengah, penuh kompromi dan tidak didasari oleh niat yang utuh. Di satu sisi, mereka dipaksa untuk mengakui dan bergaul dengan realitas yang tidak tunggal, tapi di sisi yang lain mereka enggan untuk membuang pandangan-pandangan eksklusif dalam keberagamaannya.
Karena itu, model toleransi demikian ini hanya sebatas kulit saja dan tidak memiliki akar yang kuat sebagai landasan pergaulan masyarakat global yang multikultural. Sebab di bawah sadar, ia masih menyisakan potensi kekerasan dalam wujud klaim-klaim kebenaran beragama. Dalam paradigma pseudo toleransi ini, pokok soal tentang kebenaran tunggal iman menjadi tema sentral dan absolut. Orang yang menganut model toleransi demikian, biasanya masih bernafsu atau mengincar umat beragama lain untuk dikonversi ke dalam agamanya.
Para penganut pseudo toleransi sangat sulit melepaskan diri dari sikap eksklusivisme beragama. Mereka pada umumnya mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Agama lain, menurut mereka, jikapun itu pernah diwahyukan Allah kepada para nabi-Nya, tapi belakangan keabsahannya sudah terwakilkan (baca: di-mansukh, diabrogasi) oleh agama Islam. Karena itu, siapa yang masih menganut agama di luar Islam setelah mendengar kebenaran dakwah Islam, maka keyakinannya itu tertolak dan ia tidak akan selamat di akhirat. Mereka sebetulnya mengakui bahwa sebagian dari keputusan Allah (sunnatullah) terhadap manusia adalah menjadikannya tidak satu agama. Mereka juga mengakui bahwa setiap usaha kepada homogenisasi agama adalah usaha yang sia-sia. Namun begitu, mereka juga bersikeras bahwa Islam telah menghapus kebenaran agama-agama sebelumnya berdasarkan ayat Qur’an dalam surat al-Baqarah (2: 106): “Dan ayat mana saja yang kami nasakh-kan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya.”
Pandangan Muhammad al-Ghazali –seorang tokoh Ikhwan Mesir– dalam buku al-Ta’asshub wa al-Tasâmuh bain al-Masîhiyyah wa al-Islâm (Fanatisme dan Toleransi antara Islam dan Kristen [2005: 70]) mewakili paradigma pseudo toleransi ini. Ulama tersebut menganalogikannya dengan dokter yang menyarankan makanan berupa ASI untuk bayi pada awal periode kehidupannya. Saat beranjak besar kemudian ASI itu digantikan dengan makanan yang lembut, dan ketika dewasa semua makanan itu diganti dengan makanan yang lebih baik dan sempurna. Analog dengan agama yang terus mengalami revisi di mana versi terakhir adalah yang terbaik.
Dengan konsep toleransi yang semu ini, jangankan mendakwahkan keberagamaan yang inklusif, eksklusivisme beragamapun bahkan menjadi sangat sulit untuk dihidari. Bagaimana mungkin seorang yang meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bisa membiarkan penganut agama lain hidup tenang dengan keyakinannya. Orang yang menganut paham pseudo toleransi seperti ini tidak akan pernah bisa benar-benar toleransi. Yang ia bisa hanya pura-pura toleransi. Dikatakan begitu, karena ia tidak akan berhenti mencari-cari kesempatan kapan waktunya mengkonversi keyakinan orang lain itu ke dalam Islam.
Rumusan dakwah kepada non muslim, bagi para penganut pseudo toleransi, adalah “mengajak umat manusia untuk masuk Islam, dan jika mereka menerima itu, barulah mereka disuruh untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemunkaran.” Demikian seperti dikutip dari buku Hidâyat al Mursyidin (1979: 17) karya Syeikh Ali Mahfuz, seorang da’i kondang dari al-Azhar. Karena dasarnya yang rapuh, maka model toleransi ini alih-alih menjadi solusi pluralitas sosial, yang ada justru rentan sekali menyuburkan radikalisme dan fundamentalisme beragama. Bagaimanapun juga, eksklusivisme beragama tidak akan pernah melahirkan toleransi. Sebaliknya eksklusivisme justru melegitimasi radikalisme dan segala bentuk kekerasan beragama.
Pengakuan terhadap realitas mengharuskan pembenaran terhadap realitas itu sendiri. Dengan kata lain, pengakuan terhadap pluralitas berimplikasi pada pengakuan terhadap pluralisme. Jarak antara pluralitas dan pluralisme tidak berbeda dengan das sein dan das solen, antara yang senyatanya dan yang seharusnya. Seseorang tidak akan pernah bisa menerima kenyataan pluralitas dengan tulus, selama ia masih bersikeras menolak pluralisme. Dengan demikian, rumusan KH. Hasyim Muzadi tentang bolehnya menerima pluralisme sosial tapi wajib menolak pluralisme teologis seperti dipaparkan di atas, menjadi tidak relevan. Jika yang dimaksud beliau dengan pluralisme sosial adalah sikap menerima pluralitas sosial dengan cara toleransi dan bergaul dengan akur dan damai, maka yakinlah cita-cita dakwah demikian ini dapat dipastikan tidak akan kesampaian tanpa pengakuan pluralisme teologis yang menegaskan bahwa setiap agama itu adalah benar. Karena itu, mendakwahkan toleransi yang benar tidak akan bisa terwujud selama klaim-klaim kebenaran atau eksklusivisme itu masih bersikeras dipertahankan. Sebaliknya, mendakwahkan toleransi yang masih menyisakan ruang truth claim dan eksklusivisme hanya akan melahirkan toleransi-toleransi yang “hangat-hangat tahi ayam”: laris dan populer ketika banyak terjadi konflik dan kekerasan, tapi menghilang ketika suasana relatif stabil. Dengan kata lain, pseudo toleransi tidak akan pernah benar-benar utuh dan memadai untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan, tapi bersifat sebatas tambal sulam.
Sebagai garda terdepan umat muslim, sudah saatnya para ulama sekarang ini mengubah paradigmanya tentang toleransi. Sudah saatnya beralih dari pseudo toleransi atau toleransi yang setengah-setengah, kepada toleransi yang sejati. Toleransi sejati (al tasamuh al-haqîqiy) adalah toleransi yang lahir dari pola berpikir pluralisme, yaitu toleransi yang berani menyatakan bahwa bukan hanya agama saya saja yang benar, tetapi agama orang lain juga benar. Jika semua orang menjalankan agamanya masing-masing dengan sebenar-benarnya, maka sudah pasti akan melahirkan kedamaian, ketentraman hidup dan kerjasama sosial yang sehat.
Toleransi dan pluralisme tidak perlu disikapi sebagai ancaman akidah, karena setiap orang memiliki preferensinya sendiri-sendiri. Sebagaimana baju yang saya pakai, belum tentu nyaman dipakai oleh orang lain. Berdakwah kepada non muslim dalam rumusan ini, tidak lagi identik dengan mengkonversi iman mereka, tapi cukup mengajak mereka melakukan kerjasama sosial yang sehat. Inilah toleransi yang benar dan sehat, yang semestinya dijadikan rujukan dakwah oleh para da’i dan ulama-ulama di nusantara.
Wallahu a’lam bi al-shawab.
di muat di
http://islamlib.com/id/artikel/pseudo-toleransi-metode-dakwah-al-qardlawi-dan-masa-depan-pluralisme
Langganan:
Postingan (Atom)