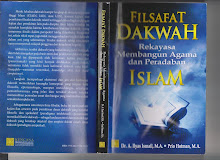Jumat, 07 September 2012
Pengkultusan Tradisi dan Pertengkaran Amar-Ma'ruf Nahi Munkar di Ruang Publik
Prio Hotman
Sejak awal mula diisukan, gerakan-gerakan pemikir muslim progressif, yang mana Jaringan Islam Liberal termasuk di dalamnya, telah berjuang setengah mati untuk mengajak umat muslim khususnya di Indonesia agar merombak (dekonstruksi) kembali warisan tradisi mereka dari masa lampau. Perombakan ini dilakukan semata-mata bukan karena mereka tidak lagi menghargai tradisi atau tidak mau memberikan tempat bagi tradisi di alam kontemporer, tapi justru karena mereka amat menghargai tradisi dan tidak menghendaki ia menghilang begitu saja bak debu yang berterbangan. Untuk bisa survive di alam kontemporer, tentu saja, tradisi mesti melakukan banyak penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian tersebut mesti dilakukan dengan melakukan penafsiran ulang (reinterpretasi) yang berani, melampaui tulisan-tulisan dan kharisma yang dikultuskan. Meminjam istilah Luthfi Assaukanie, proyek rejuvenasi atau peremajaan Islam (tradisi Islam) mesti dijalankan melalui pembaruan (reformation) dan bukan melalui pengulangan (restatement). Dengan kata lain, merujuk tradisi seharusnya dijadikan jalan untuk penelaahan, dan bukan hanya sebatas mengkutip pendapat-pendapat dari masa lampau saja.
Namun begitu, seruan kelompok muslim progressif untuk memperbarui tradisi Islam rupa-rupanya tidak mendapat respon positif dari khalayak. Ironisnya, yang ada niat tulus ini malah seringkali disimpangsiurkan menjadi fitnah-fitnah keji yang tak terperikan. Saya melihat desakan perkembangan sosial dan politik kontemporer agar umat beragama melakukan penyesuaian terhadap doktrin dan tradisi masa lalu pada akhirnya memicu terbentuknya kepribadian ganda (split personality) pada diri mereka. Di satu sisi mereka tidak berdaya untuk melepaskan diri dari belenggu dan jeratan tradisi. Di sisi yang lain, ada hasrat dan kebutuhan yang kuat untuk mempertahankan agama agar tetap sejalan dan compatible dengan perkembangan terkini umat manusia. Meskipun pertentangan demikian ini sudah lama dan sering kita simak dalam perdebatan wacana keislaman (khususnya wilayah fiqih), namun saya tidak pernah menyaksikan pertentangan yang kelihatan begitu nyata seperti pertengkaran ulama-ulama kita terkait amar ma'ruf nahi munkar yang kita saksikan belum lama ini ketika kontroversi kedatangan aktifis gender Irshad Manji dan Lady Gaga marak ditayangkan di berbagai media masa.
Pertama-tama, saya ingin menyinggung soal amar ma'ruf nahi munkar terlebih dahulu. Sekalipun bukan bagian dari rukun iman dan rukun Islam, bagi umat muslim, doktrin amar ma'ruf nahi munkar dipandang sebagai jantung yang memompa ruh kehidupan bagi komunitas masyarakat muslim. Tanpa amar ma'ruf nahi munkar, umat muslim sebagai suatu komunitas masyarakat akan lenyap eksistensinya. Demikian, karena ada satu doktrin yang diambil baik dari kitab suci al Qur'an maupun hadist nabi yang menyatakan secara umum bahwa Islam bukanlah agama individualis. Maksudnya, kesalehan individu dalam Islam tidak akan bernilai seandainya belum diterjemahkan menjadi kesalehan sosial. Untuk itu, dalam tradisi amar ma'ruf nahi munkar, umat muslim disuruh ambil bagian untuk mensalehkan sekaligus mereduksi kemaksiatan dari ruang publik. Mereka percaya dampak kesalehan dan kemaksiatan di ruang publik akan berimbas bukan hanya pada pelakunya saja, tapi juga pada mereka yang berada di sekitarnya. Dengan penilaian yang sedemikian penting itu, maka sangat wajar jika dalam literatur-litaratur fikih tradisional para ulama tidak lupa meletakkan satu bahasan tersendiri dalam bagian interaksi sosial (mu'amalah) terkait amar ma'ruf nahi munkar ini. Hanya saja, seperti halnya kesulitan dalam soal lain yang dihadapi umat muslim ketika menghadapi benturan antara ketentuan hukum agama dan perkembangan kontemporer, mereka juga menghadapi kesulitan serupa dalam soal implementasi amar ma'ruf nahi munkar ketika lebih dari separuh bangunan doktrin ini berbenturan dengan realitas sosial dan politik kontemporer yang lebih egalitarian, terbuka dan demokratis.
Karena seruan kelompok muslim progressif untuk merejuvenasi hukum-hukum tradisional diabaikan dan disia-siakan, maka konsensus dan rumusan yang baik untuk mengimplementasikan amar ma'ruf nahi munkar tanpa harus mencederai semangat atau sejalan dengan perkembangan sosial dan politik kontemporer menjadi belum terwujudkan. Hasilnya langsung dapat ditebak: pertengkaran ulama di ruang publik. Menariknya, berbeda dengan masa lalu di mana polemik para ulama hanya menghiasi lembaran-lembaran akademisi dan sangat terbatas aksesnya, saat ini pertengkaran tersebut justru dipertontonkan di ruang publik dan dapat diakses rekamannya oleh masyarakat awam dari berbagai media masa. Respon-respon dan komentarpun bertebaran di mana-mana, menjurus kepada propaganda yang kurang sehat dan tidak mendidik.
Dalam salah satu versi 'pertengkaran' terkait amar ma'ruf nahi munkar yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta belum lama ini, imam besar Masjid Istiqlal KH. Mustofa Ali Yaqub menohok lawannya, yaitu Habib Salim Al Jufri dari kubu FPI, dengan menyodorkan argumentasi amar ma'ruf nahi munkar yang menurutnya lebih bersahabat. Dengan mengutip tiga literatur kitab kuning, yakni Ihya 'Ulum al Din karangan al Ghazali, Siyasah Syar'iyyah karangan Ibn Taimiah, dan Usul al Da'wah tulisan Abdul Karim Zaida, Kiai Yaqub bersikukuh bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan dengan memunculkan kemunkaran baru. Jelasnya, amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan dengan jalan kekerasan sebetulnya juga kemunkaran baru yang menurut beliau tidak sejalan dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Di kubu lawan, Habib Al Jufri yang jamak dikenal dengan Habib Selon mencoba menangkis serangan Kiai Yaqub dengan berargumen bahwa kendatipun keterangan itu benar, namun perlu diperhatikan juga bahwa amar ma'ruf nahi munkar mewajibkan institusi hisbah. Sayangnya, sang Habib tidak cukup cerdas untuk membeberkan bahwa argumennya itu juga dimuat dalam ketiga kitab yang sama.
Saya hanya heran, entah apakah pak Kiai tidak tahu atau sengaja tidak menghiraukan bahwa ketiga ulama di atas dengan tegas menyatakan dalam tulisannya itu bahwa dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar, negara harus intervensi dalam wujud institusi hisbah (hisbah adalah institusi resmi yang dibentuk oleh kekhalifahan pada masa dinasti Islam dan diberi wewenang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan menugaskan sejumlah pekerja sipil yang disebut muhtasib. Tugas muhtasib adalah sebagai polisi moral – yang saat ini ada kemiripan dengan para aktifis ormas Islam garis keras – dan bertanggung jawab mengawasi serta mengkriminalkan setiap tindak tanduk warga negara yang bertentangan dengan ajaran agama). Namun begitu saya ingin tetap berhusnuzhan terhadap beliau. Dalam posisi ini, saya sependapat dengan Habib Selon dan memohon dengan kerendahan hati saya kepada Kiai Mustafa Yaqub agar berkenan kembali menelaah masalah hisbah ini dalam tiga literatur tersebut (Ihya 'Ulum al Din Juz 2 hlm. 308; al Siyasah al Syar'iyyah, hlm. 168; dan Usul al Da'wah hlm. 174).
Al Ghazali dalam Ihya bahkan menempatkan hisbah sebagai rukun pertama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, sebagaimana Ibn Taimiyah yang terang-terangan menyebut amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa ditegakkan tanpa unsur militerisme (al quwwah) dan intervensi negara (imârah), Abdul Karim Zaidan juga mengkategorikan pendirian institusi hisbah sebagai suatu kemutlakan bagi pemerintah (hlm. 175). Meskipun saya sependapat dengan kiai Mustafa Yaqub dalam hal amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan dengan menggunakan cara-cara anarkis dan menimbulkan kemunkaran baru, tapi kita juga mesti mempertanyakan konsistensi beliau terkait pendapat ulama-ulama yang dikutipnya tersebut. Seperti telah saya singgung di atas, saya amat menyayangkan bahwa kebanyakan ulama kita saat ini merujuk literatur-literatur tradisi hanya sebatas kutipan saja, dan bukan untuk di telaah. Akibatnya langsung dapat diterka: di satu sisi kubu pro hisbah yang diwakili Habib Selon bingung karena akan sangat beresiko (tidak mungkin?) memaksa negara untuk turut campur dalam masalah amar ma'ruf munkar dan membangun institusi hisbah untuk era kita sekarang ini. Di sisi lain kubu moderat yang diwakili Kiai Mustofa Yaqub juga bingung karena rujukan mereka terhadap tradisi tidak konsisten dan tidak lagi relevan.
Inilah gambaran fenomena yang ingin saya suguhkan kepada pembaca terkait pertengkaran ulama kita di ruang publik dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Dua kubu yang bertengkar sama-sama bingungnya. Jika kita menelusuri lebih jauh respon-respon masyarakat terkait pertengkaran ini di media masa, terutama media online, kita akan menemukan betapa kubu pro hisbah – begitu saya mengistilahkannya – menyindir keras kubu moderat sebagai 'ulama su' penjilat' (sebutan ironik dari masa klasik islam yang ditujukan untuk kelompok ulama oportunis yang mendekati pemerintah dengan jalan yang tidak terpuji dan tidak komitmen dengan ajaran agama). Dalam beberapa segi, saya menilai kritik kubu pro hisbah ini ada benarnya. Kita belum lupa bagaimana Kiai Mustofa Yaqub dan rekan-rekan ulamanya dari MUI beramai-ramai mengkroyok umat muslim penganut 'mazhab Ahmadiah' dan mendesak pemerintah agar mereka dibubarkan dengan dalil yang sama: amar ma'ruf nahi munkar. Terkait isu yang tersebut terakhir ini, kita tidak bisa lagi menempatkan Kiai Mustofa Yaqub dalam kubu moderat dari sudut manapun seperti halnya dalam isu Lady Gaga dan Irshad Manji.
Kembali lagi ke persoalan pembaruan Islam yang saya singgung di awal tulisan ini, mungkin ada harapan kebingungan seperti digambarkan di atas tidak akan terjadi seandainya sedari dulu para ulama kita mau sedikit saja menaruh hati dan mendengarkan seruan kelompok muslim progressif untuk merombak dan merumuskan ulang warisan tradisi kita yang kaya ini. Kita semua tentunya sependapat bahwa bentuk penghargaan yang baik kepada para pendahulu kita adalah bukan dengan cara 'memuseumkan' karya-karya mereka seolah sebagai barang antik yang tidak boleh disentuh. Betapapun, keberanian untuk menelaah, mengkritik, mengkaji dan meramu ulang warisan dan peninggalan mereka justru lebih berharga dan lebih memuliakan mereka.
Kendala kita satu-satunya adalah terbelenggu oleh kharismatik mereka yang begitu kuat sehingga seolah-olah tidak seorangpun boleh mengkritik atau 'mengutak-atik' karya-karya mereka jika mereka tidak memiliki kapasitas yang setara atau sebanding dengan para ulama klasik tersebut. Pertanyaannya adalah: jika tidak ada satupun muslim di muka bumi ini yang memiliki kapasitas yang sebanding dengan ulama-ulama klasik – karena yang dipentingkan saat ini adalah spesialisasi bidang tertentu, apakah lantas berarti pembaruan Islam tidak boleh dilaksanakan? Kebingungan dalam penerapan amar ma'ruf nahi munkar di alam kontemporer hanyalah salah satu akibat saja dari penolakan ajakan pembaruan Islam. Saya berani bertaruh, kebingungan-kebingungan itu akan meluas keberbagai sendi-sendi lainnya dalam kehidupan beragama di masa depan seandainya kita tetap mengabaikan atau mengacuhkan seruan untuk lebih berani melakukan pembaruan dalam Islam.
Wallahu A'lam bi al Sawwab
Langganan:
Postingan (Atom)