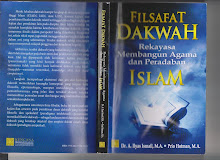Oleh : Prio Hotman*
Akselerasi informasi lewat media internet di negeri kita, ternyata bukan hanya berpengaruh secara positif pada perkembangan kognitif dan wawasan masyarakat, tapi juga secara negatif pada kecenderungan emosionalnya. Alexander (30), seorang pegawai negeri sipil dikeroyok massa ketika terbongkar identitasnya sebagai salah satu pengelola akun facebook atheis minang. Akun facebook ini dituding telah meresahkan warga karena postingan-postingannya yang bernuansa melecehkan agama. Masyarakat yang tersulut emosinya, ramai-ramai menghakimi Alex. Bukan hanya itu, Alex yang merupakan korban kekerasan dalam peristiwa tersebut, malahan ditahan dan terancam hukuman pidana lima tahun penjara. Ia dituntut karena melakukan penodaan agama.
Kasus ini rupanya bukan yang pertama. Februari awal tahun lalu, kasus persidangan Antonius, seorang terdakwa penodaan agama Islam dan Katolik melalui pamvlet, juga berujung kepada kekerasan. Kedua kasus Alex dan Antonius memiliki kesamaan dalam hal kebebasan berekspresi yang tidak mendapat restu dari masyarakat yang notabene overreligious. Iman umat beragama yang merasa terluka karena simbol-simbol agamanya disinggung, menjadi pembenaran terhadap tindak kekerasan.
Kasus-kasus tersebut mengingatkan kita pada pandangan seorang futurolog Alvin Toffler, bahwa percepatan gelombang informasi yang seharusnya menjadi instrument demokratisasi di suatu wilayah, justru dapat menjadi ancaman bagi demokratisasi itu sendiri seandainya tidak disertai oleh kedewasaan pola berpikir yang dianut oleh masyarakat tersebut. Adalah suatu sikap yang sangat naïve dalam beragama, ketika ketidaksetujuan terhadap suatu pandangan diekspresikan lewat tindak kekerasan. Kedewasaan pola berpikir dalam sebuah masyarakat demokratis yang beradab, termasuk kedewasaan dalam beragama, mengharuskan ketidakssetujuan diutarakan melalui adu argument (debat), dan bukan melalui kekerasan.
Dengan kata lain, kedua contoh kasus tersebut menegaskan kepada kita bahwa fondasi untuk menyokong iklim demokratisasi agama, dan kebebasan berekspresi di negara ini belum cukup kuat. Hal ini dikondisikan terutama oleh tiga aspek.
Pertama, lemahnya budaya ilmiah masyarakat dan menguatnya pengaruh dogma.
Dalam budaya masyarakat maju dan beradab, pola pikir dan bertindak masyarakatnya ditentukan oleh kriteria-kriteria keilmuan, diantaranya adalah rasionalitas dan argument. Sementara dalam masyarakat tradisional, yang memegang peranan adalah dogma yang notabene bersandar pada emosional. Karena itu, dogma semata-mata tidak boleh dijadikan sebagai pedoman pola hubungan sosial suatu masyarakat. Kritik terhadap simbol-simbol agama, tidak bisa disamakan dengan, misalnya, pencemaran nama baik, karena jelas-jelas yang bersangkutan masih hidup dan eksis. Sedangkan simbol-simbol agama hanya hadir dan eksis pada tataran emosional komunitas yang mengimaninya, dan karena itu kritik terhadap simbol agama tidak semestinya dipandang sebagai suatu tindak kriminal.
Ketika budaya ilmiah dalam suatu masyarakat melemah, mereka tidak bisa berpikir jernih dan rasional. Kritik terhadap simbol-simbol agama tidak bisa dibedakan lagi dari pencemaran nama baik. Karena emosi telah menggantikan rasional, maka kekerasan menjadi lebih didahulukan ketimbang adu argumentasi.
Kedua, kebijakan atau sistem perundang-undangan yang rancu.
Dalam konstitusi perundang-undangan kita, UUD 45, pasal 28E tentang hak asasi ditegaskan bahwa setiap orang bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Ini berarti konstitusi negara kita menjamin semua jenis kepercayaan, termasuk kepercayaan untuk tidak percaya pada agama, dan menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangannya itu tanpa diskriminasi. Namun di sisi lain, konstitusi kita juga mengesahkan adanya UU penodaan agama yang bernuansa diskriminatif. Oleh bebarapa ahli dan aktivis HAM, pada tahun 2010 lalu UU ini pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diujikan kembali, dan ternyata ditolak.
Dengan ditolaknya uji materil UU PNPS ini, negara dinilai telah memelihara api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat memicu beraneka macam konflik. Mereka yang menjadi korban diskriminatif, dengan adanya undang-undang ini harus menerima dua macam kekerasan, kekerasan sosial dan kekerasan hukum sekaligus.
Ketiga, mandulnya dakwah agama-agama.
Agama-agama sesuai dengan misi dakwahnya, secara ideal seharusnya mampu memberi pencerahan spiritual dan sosial kepada masyarakat. Agama-agama dihadirkan untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan seluas-luasnya kepada umat manusia. Mereka juga membenarkan tidak direstuinya penggunaan kekerasan untuk menyebarkan nilai kebaikan itu. Adalah suatu anomali, ketika disatu sisi agama-agama mengkampanyekan perdamaian, tapi di sisi lain mereka menghukumi orang yang tidak percaya dengan kekerasan.
Ini menandakan bahwa dakwah agama-agama telah kehilangan elan vitalnya dalam masyarakat. Dakwah agama-agama yang sehat, seharusnya mampu menjawab dan membantah setiap kritik dan gugatan atas doktrinnya secara tenang dan rasional, bukan dengan emosional dan kekerasan. Kasus kekerasan yang terjadi seperti diungkap di awal tulisan ini, menunjukkan bahwa dakwah agama-agama telah mengalami kemandulan.
Para pengamat, seperti Samuel Huntington, pernah menyangsikan bahwa iklim demokrasi dapat diciptakan dalam masyarakat muslim. Kemajuan politik Indonesia belakangan ini, sebagai representasi negara berpenduduk muslim dalam berdemokrasi, telah memberikan secercah harapan. Kondisi ini seharusnya dapat diperkuat oleh pemerintah melalui pembangunan iklim ilmiah di masyarakat dan peninjauan ulang perangkat hukum yang diskriminatif. Para pemuka agama dalam hal ini berperan dalam mensosialisasikan budaya dialog dan argumentasi sambil mendukung kebebasan berkeyakinan, berfikir dan berekspresi.
* penulis adalah pengajar di Univeritas Islam As Syafi'iyyah Jakarta
Senin, 30 Januari 2012
Senin, 16 Januari 2012
Homoseksualitas Dalam Sejarah : Mencari Preseden, Melampaui Misteri Para Ulama Bujang
Pencarian preseden, merupakan salah satu faktor utama yang membawa umat muslim kepada tradisi. Didorong hasrat untuk menjadi orisinil, mereka kerap bersusah-susah membongkar dalil-dalil turats dan atau sejarah yang dinilai bisa menjadi justifikasi sikap atau pandangan mereka. Beberapa di antaranya ada yang berhasil, tapi tak jarang pula dari mereka yang gagal.
Advokasi terhadap hak-hak dan pengakuan eksistensi kaum homoseksual, sejauh ini dinilai sebagai yang gagal mencari presedennya dalam sejarah Islam. Yang ada, bahkan argumentasi sejarah digunakan oleh mereka, para homophobik, sebagai dalil untuk menyisihkan kaum homoseksual dengan anggapan bahwa perbuatan mereka adalah penyimpangan. Kisah Luth dan hadist-hadist yang berisi provokasi untuk mengintimidasi mereka adalah contohnya.
Saat ini, dimana hasil riset pengetahuan sudah sedemikian maju, ditemukan fakta – fakta yang juga masih dipertentangkan – yang mengungkap unsur kealamiahan dalam formasi genetik seorang homoseksual sedari janin. Jika sepakat, fakta ini tentu merelatifkan pandangan paten yang selama ini menjadi pedoman banyak orang bahwa perilaku homoseksual adalah pilihan (constructed), dan bukannya "anugerah" (given)
Jika benar perilaku homoseksual adalah anugerah tuhan, dan bukannya konstruksi budaya atau tingkah laku yang menyimpang, maka preseden historis menjadi sangat penting keberadaannya. Ini diperlukan dalam rangka membuktikan bahwa homoseksualitas adalah fenomena alamiah yang niscaya dalam setiap fase sejarah kemanusiaan, betapapun diabaikannya. Perbedaannya, hanya kalau pada waktu itu belum ada alat untuk mengadvokasi kaum homoseksual, sehingga kemungkinannya hanya dua. Pertama, mereka harus menolak " takdir " mereka sendiri sekalipun dengan begitu mereka mengabaikan nurani mereka dan berlagak selaiknya pria sejati, betapapun dipaksakannya. Atau kedua, mendapat perlakuan keji dari masyarakat dan ancaman kekerasan tafsir teologis yang diskriminatif.
Sementara saat ini, kita telah diperkenalkan apa itu HAM, dan didukung pula oleh bukti empiris penelitian ilmiah. Dengan begitu, sekalipun penentangan keras terus berdatangan dari para homophobianist, kita, para aktivis HAM, tetap memiliki argumentasi yang kuat untuk mengadvokasi kaum homoseksual. Di pihak lain, berkah HAM dan penelitian ilmiah ini pada akhirnya memberikan alternatif ketiga bagi mereka: menjadi diri sendiri dan menuntut persamaan hak dan mencari dukungan.
Rekam jejak sejarah Islam, memberi petunjuk kepada kita bahwa eksistensi homoseksualitas, adalah fakta yang terang benderang, betapapun mau dipungkiri. Melalui tulisan seorang kritikus sejarah, Faraj Fouda, misalnya, bertajuk kebenaran yang hilang (al haqiqah al ghaibah), suka tidak suka mata kita dibuka dan dipaksa mengakui fakta ini. Kita dapat menunjuk nama khalifah al Walid Ibn Yazid dari Bani Umayyah, atau al Watsiq dan al Amin – putra Harun al Rasyid yang terkenal itu – dari Kekhalifahan Abbasiyah sebagai contohnya.
Mereka adalah orang-orang yang berani secara terang-terangan menunjukkan identitas seksual mereka di tengah masyarakat dan penafsiran teologis yang keras terhadap kaum homoseksual. Kemungkinan karena kekuasaan yang mereka miliki. Artinya, bukan tidak mungkin di luar sana, selain mereka, masih ada lagi kaum gay yang malu-malu, atau bahkan berusaha lari dari " takdir " mereka sebagai homosekual. Hanya karena mereka tidak memiliki kekuasaan, atau alat untuk mengadvokasi mereka, sehingga mereka takut mendapat sangsi kekejaman sosial dan penafsiran diskrminatif teologis.
Pada akhirnya, keterangan di atas menolak anggapan bahwa homoseksualitas lahir sebagai efek negatif budaya Barat modern yang permisif. Ini juga sekaligus mempertanyakan ulang kabar burung yang beredar bahwa katanya, Aids merupakan penyakit kutukan yang identik atau kerap dinisbatkan kepada kaum gay. Karena, faktanya homoseksualitas sudah hadir jauh-jauh hari sebelum orang mengenal apa itu Aids.
Mungkin, di antara kelompok homophobik, ada yang menyanggah " contoh-contoh di atas adalah tokoh-tokoh zindiq yang sudah terbiasa berbuat maksiat. Dengan begitu, tidak sah dijadikan sebagai preseden. Mereka juga tidak kurang bejatnya dengan para kafir Barat modern itu". Saya ingin beralih membicarakan perihal para ulama yang tidak menikah. Sebut saja seperti Mahaguru tafsir kenamaan Ibn Jarir al Thabari, pengarang al Kasysyaf, Zamakhsyari, tokoh rujukan kaum modernis, Ibn Taimiah, atau penyair dan Sufi wanita terkenal, Rabi'ah al Adawiyyah dan masih banyak lagi.
Opini kebanyakan umat muslim, ketika dihadapkan pada fakta demikian, biasanya akan berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang terlalu sibuk bergelut dalam dunia keilmuan dan agama, dan bahwa hidup mereka dibaktikan untuk umat, sehingga membuat mereka tidak sempat menikah atau hidup berumah tangga. Bagi saya, opini ini bisa saja kelihatan wajar, sebagaimana ia juga bisa menjadi mengherankan, janggal.
Di sini saya ingin menyoroti kejanggalan alasan itu. Dari sudut pandang ini, mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak asing dengan dalil-dalil fadhail al nikah (keutamaan nikah). Tidakkah lantas kita mempertanyakan apa yang membuat para ulama itu memilih untuk tidak menikah? Tidakkah seharusnya kesibukkan meriset ilmu-ilmu agama bisa beriringan dengan membina kehidupan berumah tangga? Apalagi ini telah dibuktikan oleh banyak ulama yang berhasil, dan toh, mereka adalah orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi kearifannya untuk urusan yang satu ini. Kita juga layak bertanya: tidakkah mereka mencontoh kehidupan Rasulullah yang mewariskan hikmah melalui keturunannya? Dan tidakkah mereka pernah mendengar Rasulullah bersabda " menikahlah, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya umat dari kamu"?
Tidak wajar rasanya, jika hanya karena menggeluti keilmuan, lantas mereka meninggalkan apa yang telah dicontohkan sang Rasul. Tidakkah ada alasan lain yang melampaui itu?
Belum tersedianya bukti yang kuat, membuat saya belum berani untuk menyimpulkan bahwa mereka memiliki orientasi seksual " berbeda", homosekual. Namun begitu, kejanggalan dan misteri tersebut di atas, menurut saya pantas untuk dijadikan gerbang untuk menyingkap biografi mereka secara lebih polos dan jujur.
Rasanya sangat mungkin, para ulama itu berusaha menutupi identitas homoseksualitas mereka karena adanya tekanan-tekanan baik sosial maupun penafsiran teologis yang tidak ramah terhadap kaum homoseksual pada waktu itu. Padahal, memaksakan diri untuk hidup berumah tangga, mereka tidak sanggup. Bisa saja mereka memperhitungkan bahwa dengan orientasi seksual mereka yang " berbeda" itu, tidak akan sampai pada esensi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dugaan inilah yang menyebabkan mereka beralibi, dan memilih hidup sendiri tanpa pernikahan, sekalipun hambarnya. Padahal seandainya mereka "normal", tentu akan sangat banyak orang yang bersedia menjadi partner hidup mereka. Sayangnya, pada waktu itu belum ada gerakan advokasi terhadap kaum homoseksual, apalagi konsepsi HAM dan penemuan ilmiah.
Pada akhirnya, sekalipun baru dugaan, bukan berarti ia tanpa alasan. Pendiskriminasian terhadap kaum homoseksual acapkali membuat mereka menjadi hipokrit, berpura-pura menjadi seorang straigh, dan pada akhirya merugikan bukan hanya diri mereka sendiri, tapi juga partner hidup mereka. Contoh dalam hal ini adalah banyak sekali. Sekarang, setelah semua tragedi kemanusiaan ini, masihkah kita harus mendiskriminasi mereka yang telah dikodratkan Tuhan untuk menjadi "gender ketiga" dalam lingkup kehidupan seksual.
Wallahu A'lam bi al sawwab
Advokasi terhadap hak-hak dan pengakuan eksistensi kaum homoseksual, sejauh ini dinilai sebagai yang gagal mencari presedennya dalam sejarah Islam. Yang ada, bahkan argumentasi sejarah digunakan oleh mereka, para homophobik, sebagai dalil untuk menyisihkan kaum homoseksual dengan anggapan bahwa perbuatan mereka adalah penyimpangan. Kisah Luth dan hadist-hadist yang berisi provokasi untuk mengintimidasi mereka adalah contohnya.
Saat ini, dimana hasil riset pengetahuan sudah sedemikian maju, ditemukan fakta – fakta yang juga masih dipertentangkan – yang mengungkap unsur kealamiahan dalam formasi genetik seorang homoseksual sedari janin. Jika sepakat, fakta ini tentu merelatifkan pandangan paten yang selama ini menjadi pedoman banyak orang bahwa perilaku homoseksual adalah pilihan (constructed), dan bukannya "anugerah" (given)
Jika benar perilaku homoseksual adalah anugerah tuhan, dan bukannya konstruksi budaya atau tingkah laku yang menyimpang, maka preseden historis menjadi sangat penting keberadaannya. Ini diperlukan dalam rangka membuktikan bahwa homoseksualitas adalah fenomena alamiah yang niscaya dalam setiap fase sejarah kemanusiaan, betapapun diabaikannya. Perbedaannya, hanya kalau pada waktu itu belum ada alat untuk mengadvokasi kaum homoseksual, sehingga kemungkinannya hanya dua. Pertama, mereka harus menolak " takdir " mereka sendiri sekalipun dengan begitu mereka mengabaikan nurani mereka dan berlagak selaiknya pria sejati, betapapun dipaksakannya. Atau kedua, mendapat perlakuan keji dari masyarakat dan ancaman kekerasan tafsir teologis yang diskriminatif.
Sementara saat ini, kita telah diperkenalkan apa itu HAM, dan didukung pula oleh bukti empiris penelitian ilmiah. Dengan begitu, sekalipun penentangan keras terus berdatangan dari para homophobianist, kita, para aktivis HAM, tetap memiliki argumentasi yang kuat untuk mengadvokasi kaum homoseksual. Di pihak lain, berkah HAM dan penelitian ilmiah ini pada akhirnya memberikan alternatif ketiga bagi mereka: menjadi diri sendiri dan menuntut persamaan hak dan mencari dukungan.
Rekam jejak sejarah Islam, memberi petunjuk kepada kita bahwa eksistensi homoseksualitas, adalah fakta yang terang benderang, betapapun mau dipungkiri. Melalui tulisan seorang kritikus sejarah, Faraj Fouda, misalnya, bertajuk kebenaran yang hilang (al haqiqah al ghaibah), suka tidak suka mata kita dibuka dan dipaksa mengakui fakta ini. Kita dapat menunjuk nama khalifah al Walid Ibn Yazid dari Bani Umayyah, atau al Watsiq dan al Amin – putra Harun al Rasyid yang terkenal itu – dari Kekhalifahan Abbasiyah sebagai contohnya.
Mereka adalah orang-orang yang berani secara terang-terangan menunjukkan identitas seksual mereka di tengah masyarakat dan penafsiran teologis yang keras terhadap kaum homoseksual. Kemungkinan karena kekuasaan yang mereka miliki. Artinya, bukan tidak mungkin di luar sana, selain mereka, masih ada lagi kaum gay yang malu-malu, atau bahkan berusaha lari dari " takdir " mereka sebagai homosekual. Hanya karena mereka tidak memiliki kekuasaan, atau alat untuk mengadvokasi mereka, sehingga mereka takut mendapat sangsi kekejaman sosial dan penafsiran diskrminatif teologis.
Pada akhirnya, keterangan di atas menolak anggapan bahwa homoseksualitas lahir sebagai efek negatif budaya Barat modern yang permisif. Ini juga sekaligus mempertanyakan ulang kabar burung yang beredar bahwa katanya, Aids merupakan penyakit kutukan yang identik atau kerap dinisbatkan kepada kaum gay. Karena, faktanya homoseksualitas sudah hadir jauh-jauh hari sebelum orang mengenal apa itu Aids.
Mungkin, di antara kelompok homophobik, ada yang menyanggah " contoh-contoh di atas adalah tokoh-tokoh zindiq yang sudah terbiasa berbuat maksiat. Dengan begitu, tidak sah dijadikan sebagai preseden. Mereka juga tidak kurang bejatnya dengan para kafir Barat modern itu". Saya ingin beralih membicarakan perihal para ulama yang tidak menikah. Sebut saja seperti Mahaguru tafsir kenamaan Ibn Jarir al Thabari, pengarang al Kasysyaf, Zamakhsyari, tokoh rujukan kaum modernis, Ibn Taimiah, atau penyair dan Sufi wanita terkenal, Rabi'ah al Adawiyyah dan masih banyak lagi.
Opini kebanyakan umat muslim, ketika dihadapkan pada fakta demikian, biasanya akan berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang terlalu sibuk bergelut dalam dunia keilmuan dan agama, dan bahwa hidup mereka dibaktikan untuk umat, sehingga membuat mereka tidak sempat menikah atau hidup berumah tangga. Bagi saya, opini ini bisa saja kelihatan wajar, sebagaimana ia juga bisa menjadi mengherankan, janggal.
Di sini saya ingin menyoroti kejanggalan alasan itu. Dari sudut pandang ini, mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak asing dengan dalil-dalil fadhail al nikah (keutamaan nikah). Tidakkah lantas kita mempertanyakan apa yang membuat para ulama itu memilih untuk tidak menikah? Tidakkah seharusnya kesibukkan meriset ilmu-ilmu agama bisa beriringan dengan membina kehidupan berumah tangga? Apalagi ini telah dibuktikan oleh banyak ulama yang berhasil, dan toh, mereka adalah orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi kearifannya untuk urusan yang satu ini. Kita juga layak bertanya: tidakkah mereka mencontoh kehidupan Rasulullah yang mewariskan hikmah melalui keturunannya? Dan tidakkah mereka pernah mendengar Rasulullah bersabda " menikahlah, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya umat dari kamu"?
Tidak wajar rasanya, jika hanya karena menggeluti keilmuan, lantas mereka meninggalkan apa yang telah dicontohkan sang Rasul. Tidakkah ada alasan lain yang melampaui itu?
Belum tersedianya bukti yang kuat, membuat saya belum berani untuk menyimpulkan bahwa mereka memiliki orientasi seksual " berbeda", homosekual. Namun begitu, kejanggalan dan misteri tersebut di atas, menurut saya pantas untuk dijadikan gerbang untuk menyingkap biografi mereka secara lebih polos dan jujur.
Rasanya sangat mungkin, para ulama itu berusaha menutupi identitas homoseksualitas mereka karena adanya tekanan-tekanan baik sosial maupun penafsiran teologis yang tidak ramah terhadap kaum homoseksual pada waktu itu. Padahal, memaksakan diri untuk hidup berumah tangga, mereka tidak sanggup. Bisa saja mereka memperhitungkan bahwa dengan orientasi seksual mereka yang " berbeda" itu, tidak akan sampai pada esensi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dugaan inilah yang menyebabkan mereka beralibi, dan memilih hidup sendiri tanpa pernikahan, sekalipun hambarnya. Padahal seandainya mereka "normal", tentu akan sangat banyak orang yang bersedia menjadi partner hidup mereka. Sayangnya, pada waktu itu belum ada gerakan advokasi terhadap kaum homoseksual, apalagi konsepsi HAM dan penemuan ilmiah.
Pada akhirnya, sekalipun baru dugaan, bukan berarti ia tanpa alasan. Pendiskriminasian terhadap kaum homoseksual acapkali membuat mereka menjadi hipokrit, berpura-pura menjadi seorang straigh, dan pada akhirya merugikan bukan hanya diri mereka sendiri, tapi juga partner hidup mereka. Contoh dalam hal ini adalah banyak sekali. Sekarang, setelah semua tragedi kemanusiaan ini, masihkah kita harus mendiskriminasi mereka yang telah dikodratkan Tuhan untuk menjadi "gender ketiga" dalam lingkup kehidupan seksual.
Wallahu A'lam bi al sawwab
Islam Tidak Menyuruh Bermazhab Secara Kaffah
Prio Hotman
"…ketahuilah, dalam Islam, pada prinsipnya segala sesuatu yang menyulitkan harus dihindari. Sebab, semua hal yang menyulitkan itu pasti membebani dan membelenggu kita. Karena itulah, ketentuan hukum Islam harus dibuat semudah mungkin. Sebab, pada hakekatnya Nabi kita diutus untuk membawa ketentuan yang murah, mudah, dan toleran"
Demikian komentar Fakhruddin al Razi dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat 157 QS al A'raf (lihat Tafsir al Kabir, ayat 157). Islam diturunkan kepada kita, kata al Razi, dengan ketentuan hukum yang lebih mudah ketimbang syariat umat-umat terdahulu. Agar beragama mejadi tertib, ketentuan hukum memang perlu dibuat, tetapi ketentuan hukum yang rigid dan tertutup, tidak bisa merepresentasikan tujuan beragama secara utuh, dan karena itu mesti ditinjau ulang. Dalam era globalisasi sekarang ini di mana kelompok-kelompok mazhab dalam Islam dipaksa untuk bertemu dan berdialog, memaksa umat untuk bermazhab secara kaffah dinilai sebagai tindakan arbitrer dan bertentangan dengan semangat pembebasan. Bermazhab secara kaffah adalah penyebab "taghlîl" dalam berislam.
Term taghlîl di turunkan dari QS al A'raf 157 seperti disebut di atas (wa yadla'u 'anhum israhum wa al aghlal…). Taghlîl dalam tinjauan gramatikal arab adalah isim mashdar dari kata kerja ghallala-yughallilu, maknanya mengekang atau membelenggu (to trammel). Agama selain bisa membebaskan, juga bisa menjadi belenggu yang membuat penganutnya tidak bebas, sulit berkreatifitas dan berekspresi. Taghlîl adalah suatu sikap menyekat atau mengucilkan agama dalam satu sudut perspektif atau penafsiran tertentu . Dalam penyekatan ini, seorang menjadi terbelenggu dan tidak bebas.Taghlîl dalam beragama bisa terjadi jika agama dipahami secara rigid dan ekslusive, bukan hanya dalam tataran lintas agama, tapi juga lintas mazhab dalam agama itu sendiri. Ketika taghlîl terjadi, penyekatan identitas dan intoleransi beragama akan dianggap lumrah. Dalam dosis yang terlampau tinggi, taghlîl dalam perkembangan berikutnya bisa meningkat menjadi kekerasan beragama (religious violence) seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini.
Sejarah menunjukkan kepada kita, betapa taghlîl telah menimbulkan banyak ekses-ekses negative bagi kebebasan beragama dan peradaban. Kisah tentang persaingan dua mazhab, syafi'I dan hanafi, sebagaimana dituturkan oleh Sulayman Asyqar (Asyqar, 1982: 172) dalam buku Tarikh al Fiqh al Islamy (sejarah yurisprudensi Islam) berikut adalah contoh yang sangat baik melukiskan ini.
Konon, ada seorang raja/sultan yang baru masuk Islam dan kemudian hendak menentukan mazhab apa yang mau dia anut. Untuk menarik raja ini masuk ke dalam mazhabnya, seorang ulama bernama al Marzawi dari mazhab Syafi'I menggunakan cara licik dengan cara mendemonstrasikan dua shalat menurut masing-masing mazhab di depan sang raja, tentunya dengan tidak proporsional. Pertama-tama dia mendemonstrasikan shalat dengan seapik-apiknya menurut mazhab syafi'i , kemudian ia lanjut mendemonstrasikan shalat dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan seperti terdapat mazhab hanafi. Walaupun memang kenyataannya seperti itu, dengan cara demikian ini tentulah sipelaku tidak memiliki etika atau I'tikad baik dalam memandang mazhab orang lain. Sebaliknya, orang-orang mazhab hanafi menganggap penganut syafi'I sebagai non muslim karena membolehkan berkata " aku beriman insha Allah". Lebih parah lagi, mereka dilarang menikah dengan orang yang berada di luar mazhab.
Bagi orang-orang hanafi, urusan akidah adalah masalah yang fundamental. Ia harus didasarkan pada kepastian. Kata-kata Insha Allah dalam pengakuan iman, berarti mencederai prinsip akidah Islam. Soal sesat menyesatkan demikian, mirip kita temui, sebagai contoh, pada kasus Ahmadiah sekarang ini. Bandingkan misalnya dengan mereka yang menyesatkan kelompok Ahmadiah dengan alasan urusan kenabian adalah masalah keimanan yang fundamental dan final. Meyakini nabi lagi setelah nabi Muhammad SAW berarti merusak keimanan seseorang dan karenanya ia telah keluar dari Islam.
Fenomena taghlîl bukan hanya terjadi masa lalu, dalam era kontemporer di mana demokrasi telah dijadikan ukuran sebuah bangsa yang beradab, taghlîl justru berkembang bukan hanya sebatas intoleransi beragama, lebih dari itu bermetamorphosa menjadi kekerasan (violence). Anehnya, sikap demikian ini justru ditumbuh-suburkan oleh mereka yang berada di lembaga-lembaga pemerintah, sebut saja seperti MUI, kementrian yang terlibat dalam pengesahan SKB tiga menteri, dan pemerintah daerah yang memasukkan perda-perda syariah di wilayah masing-masing. Ditambah lagi dengan ceramah-ceramah provokatif murahan yang kita bisa jumpai pada setiap even keagamaan, budaya taghlîl memperdalam jurang pemisah baik, antar maupun intern umat beragama. Kekerasan-kerasan bermotif keagamaan yang terjadi dalam satu dekade kebelakang bisa dirujuk sebagai manifestasi dari budaya taghlîl yang melanda negeri kita.
Entah sedari kapan mulanya, tiba-tiba budaya taghlîl telah berurat berakar di negeri ini. Di level akar rumput, budaya taghlîl disuburkan oleh para pemuka agama yang konservatif dengan meng-indoktrinasi umat agar beragama secara homogen. Yang lebih menyedihkan, sekolah sebagai sarana publik juga dijadikan jalan untuk menyuburkan budaya taghlîl ini. Kita bisa menemukan ini dalam pola pengajaran agama di sekolah-sekolah yang amat bias mazhab. Dengan kondisi demikian, maka amat wajar jika problem fanatisme dan kekerasan selalu menjadi momok bagi kehidupan keberagamaan di negeri ini.
Budaya taghlîl hanya bisa dilawan dengan budaya samhah yang secara diksi diterjemahkan sebagai budaya toleran dan terbuka (inklusif). Istilah ini diderivasi dari hadist nabi " innî bu'itstu bi al hanîfiyyah al samhah"/aku diutus dengan membawa risalah yang lapang dan toleran. Karena mengandaikan keterbukaan dan kelapangan, budaya samhah tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan melibatkan apa yang dalam istilah fiqih disebut "talfîq". Istilah yang begitu popular dan kontroversial dalam kajian yurisprudensi Islam ini, secara sederhana bisa dimaknai sebagai praktik keberagamaan dalam Islam yang menggabungkan beberapa pendapat ulama mazhab dalam satu masalah hukum tertentu.
Pandangan konvensional menilai talfiq dengan kacamata negatif. Mereka menjustifikasi amalan yang dilakukan dengan mencampuradukkan pendapat-pendapat mazhab yang berbeda sebagai tidak absah. Ini bisa dipahami, sebab mereka adalah orang-orang yang memuja keteraturan dan keseragaman (homogeneity). Mereka khawatir, jikalau talfiq diperbolehkan, maka orang akan menjadi gemampang atau semena-mena dalam menjalankan ketentuan agama (al inhilâl min al takâlif al syar'iyyah).
Persoalannya, kenapa logikanya tidak dibalik menjadi: bukankah umat justru jadi lebih peduli kepada kewajiban-kewajiban agama bila ketentuannya dipermudah? Bukankah kemudahan adalah prinsip dasar risalah Islam? Jika yang jadi persoalan adalah masalah tanggung jawab, bukankah akan lebih baik jika umat dicerdaskan melalui sosialisasi pendapat mazhab yang bermacam-macam itu? dan bukannya malah menyekat-nyekat mazhab sambil memagari umat dari informasi di luar mazhab yang dianutnya. Lihatlah para sahabat dan tabi'in yang tidak terepotkan dengan segala pernak-pernik fikih dan larangan talfiq ini. Begitu bebas mereka menjalani agama, dan di sisi lain mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan berwawasan luas, tidak picik tetapi toleran.
Adalah sikap yang amat paradoks, seperti kita saksikan belakangan ini, di mana para ulama menyuruh umat untuk bertoleransi dan menjaga ukhuah Islam, sementara di sisi lain mereka tetap mengecam prilaku talfiq sambil menebarkan budaya taghlîl di mana-mana. Seharusnya mazhab Islam yang bermacam-macam itu justru diperkenalkan kepada umat sebagai alternatif dan bukti kelapangan ajaran Islam seperti disabdakan oleh sang Nabi.
Dengan menerima talfiq sebagai jalan menuju budaya samhah, kehidupan intern keberagamaan yang plural di negeri ini bisa dipererat. Penerimaan talfiq ini bisa diperluas lagi untuk konteks kehidupan antar umat beragama, bukan hanya antar mazhab dalam Islam (talfiq al mazâhib), tapi juga antar agama (talfîq al syarâ'I). Tentu tidak perlu dikatakan lagi bahwa masalah ibadah ritual tidak termasuk di sini, karena hal tersebut tidak berguna sama sekali. Dengan talfiq antar syari'at ini, umat beragama dididik untuk rendah hati, mengakui bahwa seberapapun ia meyakini kebenaran agamanya, tetap saja memerlukan dialog dengan agama lain. Dengan begitu, umat beragama tidak akan dengan mudah mengklaim agamanyalah yang paling benar sambil menyalahkan agama lain.
Kini, pilihan ada di depan kita. Terserah kita mau yang mana, tentu dengan resiko masing-masing. Mulai membuka diri dan menerima talfiq demi masa depan umat beragama yang berbudaya samhah, dan mengambil resiko ke"tidak-kaffah"an bermazhab. Ataukah lebih tetap bersikukuh pada prinsip "bermazhab secara kaffah" tapi dengan mengorbankan kematangan dan kedewasaan umat dalam beragama dan tenggelam dalam budaya taghlîl.
Wallahu a'lam bi al sawwab
"…ketahuilah, dalam Islam, pada prinsipnya segala sesuatu yang menyulitkan harus dihindari. Sebab, semua hal yang menyulitkan itu pasti membebani dan membelenggu kita. Karena itulah, ketentuan hukum Islam harus dibuat semudah mungkin. Sebab, pada hakekatnya Nabi kita diutus untuk membawa ketentuan yang murah, mudah, dan toleran"
Demikian komentar Fakhruddin al Razi dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat 157 QS al A'raf (lihat Tafsir al Kabir, ayat 157). Islam diturunkan kepada kita, kata al Razi, dengan ketentuan hukum yang lebih mudah ketimbang syariat umat-umat terdahulu. Agar beragama mejadi tertib, ketentuan hukum memang perlu dibuat, tetapi ketentuan hukum yang rigid dan tertutup, tidak bisa merepresentasikan tujuan beragama secara utuh, dan karena itu mesti ditinjau ulang. Dalam era globalisasi sekarang ini di mana kelompok-kelompok mazhab dalam Islam dipaksa untuk bertemu dan berdialog, memaksa umat untuk bermazhab secara kaffah dinilai sebagai tindakan arbitrer dan bertentangan dengan semangat pembebasan. Bermazhab secara kaffah adalah penyebab "taghlîl" dalam berislam.
Term taghlîl di turunkan dari QS al A'raf 157 seperti disebut di atas (wa yadla'u 'anhum israhum wa al aghlal…). Taghlîl dalam tinjauan gramatikal arab adalah isim mashdar dari kata kerja ghallala-yughallilu, maknanya mengekang atau membelenggu (to trammel). Agama selain bisa membebaskan, juga bisa menjadi belenggu yang membuat penganutnya tidak bebas, sulit berkreatifitas dan berekspresi. Taghlîl adalah suatu sikap menyekat atau mengucilkan agama dalam satu sudut perspektif atau penafsiran tertentu . Dalam penyekatan ini, seorang menjadi terbelenggu dan tidak bebas.Taghlîl dalam beragama bisa terjadi jika agama dipahami secara rigid dan ekslusive, bukan hanya dalam tataran lintas agama, tapi juga lintas mazhab dalam agama itu sendiri. Ketika taghlîl terjadi, penyekatan identitas dan intoleransi beragama akan dianggap lumrah. Dalam dosis yang terlampau tinggi, taghlîl dalam perkembangan berikutnya bisa meningkat menjadi kekerasan beragama (religious violence) seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini.
Sejarah menunjukkan kepada kita, betapa taghlîl telah menimbulkan banyak ekses-ekses negative bagi kebebasan beragama dan peradaban. Kisah tentang persaingan dua mazhab, syafi'I dan hanafi, sebagaimana dituturkan oleh Sulayman Asyqar (Asyqar, 1982: 172) dalam buku Tarikh al Fiqh al Islamy (sejarah yurisprudensi Islam) berikut adalah contoh yang sangat baik melukiskan ini.
Konon, ada seorang raja/sultan yang baru masuk Islam dan kemudian hendak menentukan mazhab apa yang mau dia anut. Untuk menarik raja ini masuk ke dalam mazhabnya, seorang ulama bernama al Marzawi dari mazhab Syafi'I menggunakan cara licik dengan cara mendemonstrasikan dua shalat menurut masing-masing mazhab di depan sang raja, tentunya dengan tidak proporsional. Pertama-tama dia mendemonstrasikan shalat dengan seapik-apiknya menurut mazhab syafi'i , kemudian ia lanjut mendemonstrasikan shalat dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan seperti terdapat mazhab hanafi. Walaupun memang kenyataannya seperti itu, dengan cara demikian ini tentulah sipelaku tidak memiliki etika atau I'tikad baik dalam memandang mazhab orang lain. Sebaliknya, orang-orang mazhab hanafi menganggap penganut syafi'I sebagai non muslim karena membolehkan berkata " aku beriman insha Allah". Lebih parah lagi, mereka dilarang menikah dengan orang yang berada di luar mazhab.
Bagi orang-orang hanafi, urusan akidah adalah masalah yang fundamental. Ia harus didasarkan pada kepastian. Kata-kata Insha Allah dalam pengakuan iman, berarti mencederai prinsip akidah Islam. Soal sesat menyesatkan demikian, mirip kita temui, sebagai contoh, pada kasus Ahmadiah sekarang ini. Bandingkan misalnya dengan mereka yang menyesatkan kelompok Ahmadiah dengan alasan urusan kenabian adalah masalah keimanan yang fundamental dan final. Meyakini nabi lagi setelah nabi Muhammad SAW berarti merusak keimanan seseorang dan karenanya ia telah keluar dari Islam.
Fenomena taghlîl bukan hanya terjadi masa lalu, dalam era kontemporer di mana demokrasi telah dijadikan ukuran sebuah bangsa yang beradab, taghlîl justru berkembang bukan hanya sebatas intoleransi beragama, lebih dari itu bermetamorphosa menjadi kekerasan (violence). Anehnya, sikap demikian ini justru ditumbuh-suburkan oleh mereka yang berada di lembaga-lembaga pemerintah, sebut saja seperti MUI, kementrian yang terlibat dalam pengesahan SKB tiga menteri, dan pemerintah daerah yang memasukkan perda-perda syariah di wilayah masing-masing. Ditambah lagi dengan ceramah-ceramah provokatif murahan yang kita bisa jumpai pada setiap even keagamaan, budaya taghlîl memperdalam jurang pemisah baik, antar maupun intern umat beragama. Kekerasan-kerasan bermotif keagamaan yang terjadi dalam satu dekade kebelakang bisa dirujuk sebagai manifestasi dari budaya taghlîl yang melanda negeri kita.
Entah sedari kapan mulanya, tiba-tiba budaya taghlîl telah berurat berakar di negeri ini. Di level akar rumput, budaya taghlîl disuburkan oleh para pemuka agama yang konservatif dengan meng-indoktrinasi umat agar beragama secara homogen. Yang lebih menyedihkan, sekolah sebagai sarana publik juga dijadikan jalan untuk menyuburkan budaya taghlîl ini. Kita bisa menemukan ini dalam pola pengajaran agama di sekolah-sekolah yang amat bias mazhab. Dengan kondisi demikian, maka amat wajar jika problem fanatisme dan kekerasan selalu menjadi momok bagi kehidupan keberagamaan di negeri ini.
Budaya taghlîl hanya bisa dilawan dengan budaya samhah yang secara diksi diterjemahkan sebagai budaya toleran dan terbuka (inklusif). Istilah ini diderivasi dari hadist nabi " innî bu'itstu bi al hanîfiyyah al samhah"/aku diutus dengan membawa risalah yang lapang dan toleran. Karena mengandaikan keterbukaan dan kelapangan, budaya samhah tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan melibatkan apa yang dalam istilah fiqih disebut "talfîq". Istilah yang begitu popular dan kontroversial dalam kajian yurisprudensi Islam ini, secara sederhana bisa dimaknai sebagai praktik keberagamaan dalam Islam yang menggabungkan beberapa pendapat ulama mazhab dalam satu masalah hukum tertentu.
Pandangan konvensional menilai talfiq dengan kacamata negatif. Mereka menjustifikasi amalan yang dilakukan dengan mencampuradukkan pendapat-pendapat mazhab yang berbeda sebagai tidak absah. Ini bisa dipahami, sebab mereka adalah orang-orang yang memuja keteraturan dan keseragaman (homogeneity). Mereka khawatir, jikalau talfiq diperbolehkan, maka orang akan menjadi gemampang atau semena-mena dalam menjalankan ketentuan agama (al inhilâl min al takâlif al syar'iyyah).
Persoalannya, kenapa logikanya tidak dibalik menjadi: bukankah umat justru jadi lebih peduli kepada kewajiban-kewajiban agama bila ketentuannya dipermudah? Bukankah kemudahan adalah prinsip dasar risalah Islam? Jika yang jadi persoalan adalah masalah tanggung jawab, bukankah akan lebih baik jika umat dicerdaskan melalui sosialisasi pendapat mazhab yang bermacam-macam itu? dan bukannya malah menyekat-nyekat mazhab sambil memagari umat dari informasi di luar mazhab yang dianutnya. Lihatlah para sahabat dan tabi'in yang tidak terepotkan dengan segala pernak-pernik fikih dan larangan talfiq ini. Begitu bebas mereka menjalani agama, dan di sisi lain mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan berwawasan luas, tidak picik tetapi toleran.
Adalah sikap yang amat paradoks, seperti kita saksikan belakangan ini, di mana para ulama menyuruh umat untuk bertoleransi dan menjaga ukhuah Islam, sementara di sisi lain mereka tetap mengecam prilaku talfiq sambil menebarkan budaya taghlîl di mana-mana. Seharusnya mazhab Islam yang bermacam-macam itu justru diperkenalkan kepada umat sebagai alternatif dan bukti kelapangan ajaran Islam seperti disabdakan oleh sang Nabi.
Dengan menerima talfiq sebagai jalan menuju budaya samhah, kehidupan intern keberagamaan yang plural di negeri ini bisa dipererat. Penerimaan talfiq ini bisa diperluas lagi untuk konteks kehidupan antar umat beragama, bukan hanya antar mazhab dalam Islam (talfiq al mazâhib), tapi juga antar agama (talfîq al syarâ'I). Tentu tidak perlu dikatakan lagi bahwa masalah ibadah ritual tidak termasuk di sini, karena hal tersebut tidak berguna sama sekali. Dengan talfiq antar syari'at ini, umat beragama dididik untuk rendah hati, mengakui bahwa seberapapun ia meyakini kebenaran agamanya, tetap saja memerlukan dialog dengan agama lain. Dengan begitu, umat beragama tidak akan dengan mudah mengklaim agamanyalah yang paling benar sambil menyalahkan agama lain.
Kini, pilihan ada di depan kita. Terserah kita mau yang mana, tentu dengan resiko masing-masing. Mulai membuka diri dan menerima talfiq demi masa depan umat beragama yang berbudaya samhah, dan mengambil resiko ke"tidak-kaffah"an bermazhab. Ataukah lebih tetap bersikukuh pada prinsip "bermazhab secara kaffah" tapi dengan mengorbankan kematangan dan kedewasaan umat dalam beragama dan tenggelam dalam budaya taghlîl.
Wallahu a'lam bi al sawwab
Membaca Ulang Amar Ma'ruf-Nahi Munkar
Oleh Prio Hotman
Bagi agama-agama evangelikan, misi dan proselitisasi menjadi dogma yang tidak bisa dipungkiri. Seperti diyakini oleh penganut agama-agama ini, keimanan seorang yang beriman (the believer) tidak mencukupi hanya di dalam hati atau diikrarkan melalui lisan saja. Lebih dari itu, seorang beriman memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran keyakinannya itu kepada orang lain. Dengan kata lain, agama-agama evangelik menolak privatisasi iman yang berpretensi selamat sendirian, sebaliknya, ia menuntut pengikutnya untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang kepada keselamatan. Dalam kristen, misalnya, ajaran ini termanifestasi dalam mesianisme, paham bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Sedangkan dalam Islam, ajaran ini lahir dalam bentuk dakwah: amar ma'ruf dan nahi munkar. Melalui tulisan singkat ini, saya ingin membatasi diri pada yang tersebut terakhir dan merefleksikannya dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia.
Ortodoksi Islam telah menjadikan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagai salah satu tema sentral dalam wacana teologis. Melalui penelusuran literatur-literatur Islam klasik, tema ini biasanya disuguhkan kepada kita dalam suatu bab khusus dalam lingkup kajian interaksi sosial (mu'amalah). Ihya 'Ulum al Din, kitab rujukan standar kaum sunni karangan al Ghazali misalnya, memberi ruang tidak kurang dari 30 halaman khusus membahas masalah ini dipandang dari sudut individu, sosial, hingga negara. Sementara itu, Ibn Taimiah seorang teolog sunni terkenal bermazhab hambali, bahkan memuat masalah ini dalam satu risalah tersendiri yang kemudian ia beri judul sesuai dengan temanya, al amru bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar. Merasa masalah ini begitu penting, teolog-teolog muslim kontemporer menegaskan kembali doktrin ini dalam buku-buku mereka. Namun begitu, dengan sedikit simplifikasi, saya ingin mengatakan bahwa doktrin amar ma'ruf nahi munkar seperti dikonsep oleh teolog-teolog muslim klasik tersebut cenderung bermasalah dilihat dari sudut epistemologi jika kita bandingkan dengan konteks sosiologis-politis masyarakat modern. Masalah itu makin diperparah oleh penegasan kembali –untuk menghindar dari istilah membeok– teolog-teolog muslim kontemporer yang kurang cerdas mengartikulasikan doktrin amar ma'ruf nahi munkar ini dalam koteks kekinian dan kedisinian umat muslim khususnya, dan masyarakat global umumnya. Kontras saja, kesenjangan ini berlanjut kepada ketegangan dan benturan antara keyakinan dan kenyataan yang harus dihadapi umat beriman.
Jika mau jujur, membincangkan amar ma'ruf nahi munkar dalam bingkai kebebasan beragama menjadi sangat melelahkan. Bukan hanya karena dituntut untuk mendamaikan antara doktrin ini dan kebutuhan masyarakat modern, tapi juga karena sering terjadi ketegangan antara kecenderungan ekslusivisme di dalamnya dengan nas-nas agama sendiri yang terang-terang membela kebebasan beragama dan toleransi. Secara teoritikal, benar bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan (ta'arudl) antara amar ma'ruf nahi munkar dengan kebebasan beragama. Tapi secara faktual dan praktikal, umat muslim harus mengakui bahwa ada persoalan tarik menarik antara dua konsep yang nota bene sama-sama berasal dari ajaran pokok Islam ini. Umat muslim harus membuka mata bahwa kekerasan pernah terjadi dalam sejarah mereka di bawah nama amar ma'ruf nahi munkar. Doktrin yang kemudian dijadikan salah satu dari lima ajaran dasar kelompok muktazilah ini, tercatat sejarah pernah dilegitimasi sebagai rujukan untuk mengeksekusi orang-orang yang berbeda paham dengan penguasa. Kelompok ekstrim khawarij bahkan menjadikan kekerasan sebagai wasilah untuk menyelamatkan orang melalui amar ma'ruf nahi munkar, sungguh ironi.
Berbeda dengan kedua kelompok di atas, Ibn Taimiah mewakili mazhab sunni, memang menolak amar ma'ruf nahi munkar sebagai legitimasi tindakan makar terhadap negara. Tapi dari sudut pandang kebebasan beragama dan toleransi, kelompok yang tersebut terakhir ini juga tidak memiliki pandangan amar ma'ruf nahi munkar yang lebih baik dari yang pertama. Mereka membuat konsep wilâyat al hisbah, yaitu jabatan eksekutor amar ma'ruf nahi munkar yang diangkat negara untuk mengawasi moral warga masyarakat atau sering disebut sebagai polisi moral. Negara memberi wewenang kepada polisi moral untuk mengincim-incim setiap tindak-tanduk warga negara dan menghukum mereka yang dianggap menyalahi syariat. Menurut mereka, manusia tidak cukup diawasi oleh malaikat raqib-atid saja, tapi perlu ada aparatur khusus yang mengatur apa yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan orang. Celakanya, dalam alam modern ini, pandangan primitif abad pertengahan ini masih diadopsi oleh sebagian negara-negara muslim seperti Saudi Arabia, Sudan, Iran dan provinsi Aceh di Indonesia.
Dalam melakukan aksi kekerasannya, kelompok-kelompok Islam garis keras juga kerap menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tameng untuk menghancurkan diskotik, bar-bar, hingga rumah-rumah ibadah. Penganiayaan warga Ahmadiah beberapa waktu yang lalu, juga dikobarkan di bawah bendera amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan menurut Muhammad Shahrur, amar ma'ruf nahi munkar adalah salah dari empat doktrin yang ditengarai menjadi pemicu lahirnya tindak terorisme di dunia Islam (tiga lainnya adalah al wala wa al barra, al jihad wa al qital, dan mas'alat al riddah). Di bawah bendera amar ma'ruf nahi munkar, mereka beranggapan perlu mengambil wewenang malaikat raqib-atid dan mengawasi tindak tanduk setiap orang. Atas nama amar ma'ruf nahi munkar pula, mereka merasa perlu memberantas "paham-paham sesat" dan "menyimpang". Mereka meyakini bahwa Allah akan mendatangkan bencana alam, sebagai siksa bagi mereka yang melihat kemunkaran tapi diam saja, - sungguh sebuah penafsiran agama yang menggelikan di tengah perkembangan canggih teknologi dan sains modern. Atas dasar logika ini, mereka merasa terpanggil untuk menumpas setiap kemunkaran yang mereka temui, - berdasar hadist nabi - dengan kekuatan atau ucapan kalau bisa, dan jika tidak maka melalui hati dengan catatan dinilai sebagai orang yang rendah imannya (dzawi al Iman al dha'if).
Pandangan ortodoksi seperti ini, tentu tidak bisa dicerna oleh logika masyarakat modern yang menghargai perbedaan, kebebasan, dan memberikan otonomi penuh kepada manusia untuk mengatur dirinya sendiri. Pada era di mana pilihan dan konsekuensi setiap tindakan manusia sangat dijunjung tinggi, maka pengawasan dan tekanan terhadap kebebasan individu menjadi sangat tidak manusiawi. Agama harus belajar percaya dan melihat manusia dari sudut pandang positif, dan menghilangkan mitos yang menyatakan jika manusia dilepas tanpa pengawasan bisa mendatangkan kekacauan dan kerusakan. Bukankah al Qur'an menegaskan bahwa manusia itu pada dasarnya cenderung pada kebaikan " innahu lihubbi al khairi lasyadid"? Bukankah pula pilihan manusia begitu ditoleransi oleh al Qur'an, termasuk pilihan untuk menjadi tidak baik "faman sya'a falyu'min, faman sya'a fal yakfur"? lantas alasan apalagi yang menolak memberikan otonomi penuh kepada manusia untuk mengatur dirinya sendiri.
Jika memang demikian, bisakah kita mengaksentuasikan iman kita tanpa melanggar kebebasan dan pilihan orang lain? Bisakah kita berdakwah: ber-amar ma'ruf nahi munkar tanpa harus menjadi psikopat yang haus darah? Dan bisakah kita menjadi mukmin yang otentik sekaligus menjadi toleran sejati?
Adalah Muhammad Sharur, seorang pemikir muslim progressif dari Suriah, satu di antara seribu tokoh muslim yang relatif berhasil menjelaskan doktrin amar ma'ruf nahi munkar ini dari konteks kebutuhan masyarakat modern. Melalui buku Tajfîf Manâbi al Irhâb, setidaknya ada tujuh poin yang bisa disarikan dari pandangan tokoh tersebut tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar yang benar di abad 21 ini. pertama-tama ia mengkritik isi hadist tentang taghyir al munkar yang terkenal itu dan menilainya bertentangan dengan ruh QS al Nisa/4:34 tentang sikap keras kepada istri. Menurut Shahrur, isi hadist tersebut menyuruh mendahulukan sikap keras terlebih dahulu dari sikap lembut (min al aghlazh ila al althaf). Ini berkebalikan dengan semangat surah al Nisa yang menyuruh berdakwah secara bertingkat dari mulai yang lembut terlebih dahulu baru yang keras (min al althaf ila aghlazh). Bagi Shahrur, kalaupun hadist ini sahih, ia menjelaskan kasus spesifik tertentu yang tidak bisa digeneralisir.
Kedua, amar ma'ruf nahi munkar di era modern ini, menurut Shahrur mensyaratkan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta kebebasan berkeyakinan dan berekspresi tanpa ada rasa takut. Dengan demikian, pilihan-pilihan manusia itu menjadi jujur dan ikhlas, baik ataupun buruk, atas dasar kesadarannya, dan bukan karena diawasi dan dipaksa. Tanpa semua kebebasan ini, amar ma'ruf nahi munkar tidak lebih dari cemeti yang memaksa manusia untuk menjadi mahluk-mahluk hipokrit.
Ketiga, dalam ranah sosial, amar ma'ruf nahi munkar disosialisasikan melalui asosiasi-asosiasi masyarakat sipil lewat penyuluhan dan pencerahan, penerangan kepada masyarakat bukan melalui paksaan, pengawasan dan ancaman aparatur negara.
Keempat, dalam ranah politik, amar ma'ruf nahi munkar mensahkan adanya pihak oposisi yang memberi kritik terhadap negara. Seperti diketahui, negara adalah institusi yang rentan terkena korupsi. Di sinilah peran oposisi dalam membongkar dan membeberkan setiap cacat dan kerusakan program yang dijalankan pemerintah terpilih melalui prosedur yang legal dan beradab. Tentu saja, kata Sharur, kondisi ini mensaratkan negara itu adalah demokratis, dan bukan represif (daulah dlabthin, la daulah qama'in).
Kelima, dalam kehidupan bernegara, amar ma'ruf nahi munkar itu diaplikasikan melalui penerapan undang-undang yang telah disepakati bersama. Ketaatan kepada undang-undang ini (al thâ'ah li al qawânin al nâfidzah), bagi warga negara ditujukan demi memelihara ketertiban umum dan melindungi kebebasan setiap individu.
Keenam, terkait dengan penerapan undang-undang negara, maka aspek hukum yang diikat di dalamnya adalah hanya segi-segi kehidupan yang mengatur wilayah publik saja. Karena itu, amar ma'ruf nahi munkar dalam level negara tidak seharusnya mengatur wilayah-wilayah privat seperti keimanan, ibadah ritual, dan pola kehidupan seseorang. Adapun yang tersebut terakhir ini, biarlah menjadi bagian amar ma'ruf nahi munkar dalam level masyarakat sipil saja.
Ketujuh, Shahrur mewanti-wanti kaum muslimin supaya jangan tertipu, bahwa ormas-ormas dan partai Islam yang mengaku memiliki agenda dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sekarang ini sejatinya tidak lebih dari dakwah sektarian yang terikat dengan kepentingan kelompok mereka saja. Mensikapi mereka, cukup sebagaimana kita mensikapi ormas dan partai sekuler saja. Tidak lebih, dan tidak kurang.
Pesan empatik yang terkandung dalam doktrin dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, sebetulnya sah-sah saja jika disalurkan secara benar. Pada hakekatnya dakwah memberikan kebebasan seluas-luasnya pada audien (mad'u) untuk menerima atau menolak. Nabi diberingatkan "engkau hanyalah seorang penyampai (al balagh)". Dan karena hidayah adalah sepenuhnya prerogatif Allah, maka berkeinginan menyelamatkan orang dengan merampas kebebasan dan menindas orang lain adalah sebuah ironi yang perlu dipertanyakan.
Wallahu A'lam bi al Sawwab
Bagi agama-agama evangelikan, misi dan proselitisasi menjadi dogma yang tidak bisa dipungkiri. Seperti diyakini oleh penganut agama-agama ini, keimanan seorang yang beriman (the believer) tidak mencukupi hanya di dalam hati atau diikrarkan melalui lisan saja. Lebih dari itu, seorang beriman memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran keyakinannya itu kepada orang lain. Dengan kata lain, agama-agama evangelik menolak privatisasi iman yang berpretensi selamat sendirian, sebaliknya, ia menuntut pengikutnya untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang kepada keselamatan. Dalam kristen, misalnya, ajaran ini termanifestasi dalam mesianisme, paham bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Sedangkan dalam Islam, ajaran ini lahir dalam bentuk dakwah: amar ma'ruf dan nahi munkar. Melalui tulisan singkat ini, saya ingin membatasi diri pada yang tersebut terakhir dan merefleksikannya dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia.
Ortodoksi Islam telah menjadikan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagai salah satu tema sentral dalam wacana teologis. Melalui penelusuran literatur-literatur Islam klasik, tema ini biasanya disuguhkan kepada kita dalam suatu bab khusus dalam lingkup kajian interaksi sosial (mu'amalah). Ihya 'Ulum al Din, kitab rujukan standar kaum sunni karangan al Ghazali misalnya, memberi ruang tidak kurang dari 30 halaman khusus membahas masalah ini dipandang dari sudut individu, sosial, hingga negara. Sementara itu, Ibn Taimiah seorang teolog sunni terkenal bermazhab hambali, bahkan memuat masalah ini dalam satu risalah tersendiri yang kemudian ia beri judul sesuai dengan temanya, al amru bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar. Merasa masalah ini begitu penting, teolog-teolog muslim kontemporer menegaskan kembali doktrin ini dalam buku-buku mereka. Namun begitu, dengan sedikit simplifikasi, saya ingin mengatakan bahwa doktrin amar ma'ruf nahi munkar seperti dikonsep oleh teolog-teolog muslim klasik tersebut cenderung bermasalah dilihat dari sudut epistemologi jika kita bandingkan dengan konteks sosiologis-politis masyarakat modern. Masalah itu makin diperparah oleh penegasan kembali –untuk menghindar dari istilah membeok– teolog-teolog muslim kontemporer yang kurang cerdas mengartikulasikan doktrin amar ma'ruf nahi munkar ini dalam koteks kekinian dan kedisinian umat muslim khususnya, dan masyarakat global umumnya. Kontras saja, kesenjangan ini berlanjut kepada ketegangan dan benturan antara keyakinan dan kenyataan yang harus dihadapi umat beriman.
Jika mau jujur, membincangkan amar ma'ruf nahi munkar dalam bingkai kebebasan beragama menjadi sangat melelahkan. Bukan hanya karena dituntut untuk mendamaikan antara doktrin ini dan kebutuhan masyarakat modern, tapi juga karena sering terjadi ketegangan antara kecenderungan ekslusivisme di dalamnya dengan nas-nas agama sendiri yang terang-terang membela kebebasan beragama dan toleransi. Secara teoritikal, benar bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan (ta'arudl) antara amar ma'ruf nahi munkar dengan kebebasan beragama. Tapi secara faktual dan praktikal, umat muslim harus mengakui bahwa ada persoalan tarik menarik antara dua konsep yang nota bene sama-sama berasal dari ajaran pokok Islam ini. Umat muslim harus membuka mata bahwa kekerasan pernah terjadi dalam sejarah mereka di bawah nama amar ma'ruf nahi munkar. Doktrin yang kemudian dijadikan salah satu dari lima ajaran dasar kelompok muktazilah ini, tercatat sejarah pernah dilegitimasi sebagai rujukan untuk mengeksekusi orang-orang yang berbeda paham dengan penguasa. Kelompok ekstrim khawarij bahkan menjadikan kekerasan sebagai wasilah untuk menyelamatkan orang melalui amar ma'ruf nahi munkar, sungguh ironi.
Berbeda dengan kedua kelompok di atas, Ibn Taimiah mewakili mazhab sunni, memang menolak amar ma'ruf nahi munkar sebagai legitimasi tindakan makar terhadap negara. Tapi dari sudut pandang kebebasan beragama dan toleransi, kelompok yang tersebut terakhir ini juga tidak memiliki pandangan amar ma'ruf nahi munkar yang lebih baik dari yang pertama. Mereka membuat konsep wilâyat al hisbah, yaitu jabatan eksekutor amar ma'ruf nahi munkar yang diangkat negara untuk mengawasi moral warga masyarakat atau sering disebut sebagai polisi moral. Negara memberi wewenang kepada polisi moral untuk mengincim-incim setiap tindak-tanduk warga negara dan menghukum mereka yang dianggap menyalahi syariat. Menurut mereka, manusia tidak cukup diawasi oleh malaikat raqib-atid saja, tapi perlu ada aparatur khusus yang mengatur apa yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan orang. Celakanya, dalam alam modern ini, pandangan primitif abad pertengahan ini masih diadopsi oleh sebagian negara-negara muslim seperti Saudi Arabia, Sudan, Iran dan provinsi Aceh di Indonesia.
Dalam melakukan aksi kekerasannya, kelompok-kelompok Islam garis keras juga kerap menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tameng untuk menghancurkan diskotik, bar-bar, hingga rumah-rumah ibadah. Penganiayaan warga Ahmadiah beberapa waktu yang lalu, juga dikobarkan di bawah bendera amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan menurut Muhammad Shahrur, amar ma'ruf nahi munkar adalah salah dari empat doktrin yang ditengarai menjadi pemicu lahirnya tindak terorisme di dunia Islam (tiga lainnya adalah al wala wa al barra, al jihad wa al qital, dan mas'alat al riddah). Di bawah bendera amar ma'ruf nahi munkar, mereka beranggapan perlu mengambil wewenang malaikat raqib-atid dan mengawasi tindak tanduk setiap orang. Atas nama amar ma'ruf nahi munkar pula, mereka merasa perlu memberantas "paham-paham sesat" dan "menyimpang". Mereka meyakini bahwa Allah akan mendatangkan bencana alam, sebagai siksa bagi mereka yang melihat kemunkaran tapi diam saja, - sungguh sebuah penafsiran agama yang menggelikan di tengah perkembangan canggih teknologi dan sains modern. Atas dasar logika ini, mereka merasa terpanggil untuk menumpas setiap kemunkaran yang mereka temui, - berdasar hadist nabi - dengan kekuatan atau ucapan kalau bisa, dan jika tidak maka melalui hati dengan catatan dinilai sebagai orang yang rendah imannya (dzawi al Iman al dha'if).
Pandangan ortodoksi seperti ini, tentu tidak bisa dicerna oleh logika masyarakat modern yang menghargai perbedaan, kebebasan, dan memberikan otonomi penuh kepada manusia untuk mengatur dirinya sendiri. Pada era di mana pilihan dan konsekuensi setiap tindakan manusia sangat dijunjung tinggi, maka pengawasan dan tekanan terhadap kebebasan individu menjadi sangat tidak manusiawi. Agama harus belajar percaya dan melihat manusia dari sudut pandang positif, dan menghilangkan mitos yang menyatakan jika manusia dilepas tanpa pengawasan bisa mendatangkan kekacauan dan kerusakan. Bukankah al Qur'an menegaskan bahwa manusia itu pada dasarnya cenderung pada kebaikan " innahu lihubbi al khairi lasyadid"? Bukankah pula pilihan manusia begitu ditoleransi oleh al Qur'an, termasuk pilihan untuk menjadi tidak baik "faman sya'a falyu'min, faman sya'a fal yakfur"? lantas alasan apalagi yang menolak memberikan otonomi penuh kepada manusia untuk mengatur dirinya sendiri.
Jika memang demikian, bisakah kita mengaksentuasikan iman kita tanpa melanggar kebebasan dan pilihan orang lain? Bisakah kita berdakwah: ber-amar ma'ruf nahi munkar tanpa harus menjadi psikopat yang haus darah? Dan bisakah kita menjadi mukmin yang otentik sekaligus menjadi toleran sejati?
Adalah Muhammad Sharur, seorang pemikir muslim progressif dari Suriah, satu di antara seribu tokoh muslim yang relatif berhasil menjelaskan doktrin amar ma'ruf nahi munkar ini dari konteks kebutuhan masyarakat modern. Melalui buku Tajfîf Manâbi al Irhâb, setidaknya ada tujuh poin yang bisa disarikan dari pandangan tokoh tersebut tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar yang benar di abad 21 ini. pertama-tama ia mengkritik isi hadist tentang taghyir al munkar yang terkenal itu dan menilainya bertentangan dengan ruh QS al Nisa/4:34 tentang sikap keras kepada istri. Menurut Shahrur, isi hadist tersebut menyuruh mendahulukan sikap keras terlebih dahulu dari sikap lembut (min al aghlazh ila al althaf). Ini berkebalikan dengan semangat surah al Nisa yang menyuruh berdakwah secara bertingkat dari mulai yang lembut terlebih dahulu baru yang keras (min al althaf ila aghlazh). Bagi Shahrur, kalaupun hadist ini sahih, ia menjelaskan kasus spesifik tertentu yang tidak bisa digeneralisir.
Kedua, amar ma'ruf nahi munkar di era modern ini, menurut Shahrur mensyaratkan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta kebebasan berkeyakinan dan berekspresi tanpa ada rasa takut. Dengan demikian, pilihan-pilihan manusia itu menjadi jujur dan ikhlas, baik ataupun buruk, atas dasar kesadarannya, dan bukan karena diawasi dan dipaksa. Tanpa semua kebebasan ini, amar ma'ruf nahi munkar tidak lebih dari cemeti yang memaksa manusia untuk menjadi mahluk-mahluk hipokrit.
Ketiga, dalam ranah sosial, amar ma'ruf nahi munkar disosialisasikan melalui asosiasi-asosiasi masyarakat sipil lewat penyuluhan dan pencerahan, penerangan kepada masyarakat bukan melalui paksaan, pengawasan dan ancaman aparatur negara.
Keempat, dalam ranah politik, amar ma'ruf nahi munkar mensahkan adanya pihak oposisi yang memberi kritik terhadap negara. Seperti diketahui, negara adalah institusi yang rentan terkena korupsi. Di sinilah peran oposisi dalam membongkar dan membeberkan setiap cacat dan kerusakan program yang dijalankan pemerintah terpilih melalui prosedur yang legal dan beradab. Tentu saja, kata Sharur, kondisi ini mensaratkan negara itu adalah demokratis, dan bukan represif (daulah dlabthin, la daulah qama'in).
Kelima, dalam kehidupan bernegara, amar ma'ruf nahi munkar itu diaplikasikan melalui penerapan undang-undang yang telah disepakati bersama. Ketaatan kepada undang-undang ini (al thâ'ah li al qawânin al nâfidzah), bagi warga negara ditujukan demi memelihara ketertiban umum dan melindungi kebebasan setiap individu.
Keenam, terkait dengan penerapan undang-undang negara, maka aspek hukum yang diikat di dalamnya adalah hanya segi-segi kehidupan yang mengatur wilayah publik saja. Karena itu, amar ma'ruf nahi munkar dalam level negara tidak seharusnya mengatur wilayah-wilayah privat seperti keimanan, ibadah ritual, dan pola kehidupan seseorang. Adapun yang tersebut terakhir ini, biarlah menjadi bagian amar ma'ruf nahi munkar dalam level masyarakat sipil saja.
Ketujuh, Shahrur mewanti-wanti kaum muslimin supaya jangan tertipu, bahwa ormas-ormas dan partai Islam yang mengaku memiliki agenda dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sekarang ini sejatinya tidak lebih dari dakwah sektarian yang terikat dengan kepentingan kelompok mereka saja. Mensikapi mereka, cukup sebagaimana kita mensikapi ormas dan partai sekuler saja. Tidak lebih, dan tidak kurang.
Pesan empatik yang terkandung dalam doktrin dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, sebetulnya sah-sah saja jika disalurkan secara benar. Pada hakekatnya dakwah memberikan kebebasan seluas-luasnya pada audien (mad'u) untuk menerima atau menolak. Nabi diberingatkan "engkau hanyalah seorang penyampai (al balagh)". Dan karena hidayah adalah sepenuhnya prerogatif Allah, maka berkeinginan menyelamatkan orang dengan merampas kebebasan dan menindas orang lain adalah sebuah ironi yang perlu dipertanyakan.
Wallahu A'lam bi al Sawwab
Langganan:
Postingan (Atom)